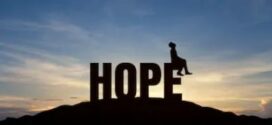Keluarga Kristen akan menemukan jati dirinya bukan dalam kesempurnaan manusiawi kedua insan (suami-istri), melainkan dalam terang kasih Kristus dan dalam persekutuan Allah Trinitas yang kekal. Corak hidup kristosentris-trinitaris bukan sekadar istilah teologis yang terdengar asing atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia adalah napas kehidupan itu sendiri seperti udara yang menghidupi setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap percakapan di dalam rumah.
Ketika kita berbicara tentang keluarga yang kristosentris, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang keluarga yang menempatkan Kristus bukan hanya sebagai tamu kehormatan yang sesekali dikunjungi di hari Minggu, melainkan sebagai jantung yang memompa darah kehidupan ke seluruh anggota tubuh keluarga. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Kolose 1:16-17, “Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia.” Kristus bukan hanya fondasi, tetapi juga arah tujuan. Bukan hanya awal, tetapi juga akhir dari segala perjalanan keluarga.
Dalam iman kepada Kristus inilah, keluarga belajar bagaimana mengenal kasih Allah Bapa, yaitu kasih yang menciptakan, yang memelihara, yang tidak pernah melepaskan. Dalam Kristus Sang Firman pula, keluarga berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang senantiasa menghibur di tengah air mata, yang menguatkan di saat lelah, dan yang menerangi jalan ketika gelap mengepung. Dengan demikian, pondasi dan tujuan hidup keluarga Kristen bersumber dari hakikat Allah yang esa dalam persekutuan kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Karl Barth, dalam magnum opus-nya Church Dogmatics (CD III/4), pernah menulis bahwa perkawinan adalah covenant relationship. Hakikat perkawinan bukan sekadar kontrak yang bisa dibatalkan ketika salah satu pihak mengingkari janjinya, melainkan perjanjian kasih yang mencerminkan hubungan Allah dengan umat-Nya. Ini adalah kasih yang bertahan melampaui perasaan, melampaui kegagalan, dan melampaui kerapuhan manusiawi.
Kasih Allah Trinitas itu tampak nyata sejak awal, sejak momen sakral ketika seorang laki-laki dan perempuan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dalam kebaktian peneguhan perkawinan itu mereka berjanji, bukan hanya kepada satu sama lain, tetapi kepada Allah yang kudus. Dalam konteks itu, seorang pendeta meneguhkan mereka dengan kata-kata yang bukan sekadar rumusan ritual, melainkan deklarasi ilahi, yaitu “Aku meneguhkan perkawinanmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.”
Kata-kata itu sederhana, namun penuh makna dan berdampak besar. Kata-kata itu singkat, namun membuka pintu kekekalan. Dari momen sakral itulah lahir satu ikatan yang bukan sekadar kontrak sosial yang bisa diubah sesuai tren zaman, melainkan perjanjian kudus yang diikat oleh Allah sendiri, Dietrich Bonhoeffer, dalam surat-suratnya dari penjara (Letters and Papers from Prison), pernah menulis bahwa perkawinan adalah institusi yang lebih besar dari dua individu. Di dalamnya, Kristus menjadi penopang. Tuhan Yesus bukan hanya saksi, tetapi pondasi iman yang mampu menahan saat badai menerjang.
Sebagaimana firman Tuhan menyatakan dengan jelas dalam Markus 10:9, “Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia,” demikian pula keluarga Kristen dipanggil untuk tetap setia dalam kesatuan hingga maut memisahkan mereka. Ini bukanlah klaim yang mudah di zaman di mana perceraian dipandang sebagai solusi praktis bagi setiap ketidakcocokan. Sebaliknya ini adalah panggilan radikal untuk percaya bahwa Allah yang mengikat juga adalah Allah yang menguatkan.
Bapa Agustinus dari Hippo, dalam karyanya De Bono Conjugali, mengidentifikasi tiga kebaikan (bona) perkawinan, yaitu: proles (keturunan), fides (kesetiaan), dan sacramentum (ikatan sakramental yang tidak terceraikan). Yang ketiga inilah yang paling mendasar bahwa perkawinan Kristen memiliki dimensi ilahi yang melampaui perhitungan manusiawi tentang untung-rugi, cocok atau tidak cocok.
John Calvin, dalam Institutes of the Christian Religion (Book IV, Chapter 19), dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ordinansi ilahi yang kudus. Ia bukan sekadar institusi sosial yang dirancang manusia untuk kenyamanan, melainkan pemberian Tuhan yang dirancang untuk kemuliaan-Nya. Karena itu, perceraian, meskipun dalam “keadaan tertentu” dapat dibenarkan secara pastoral tidak pernah menjadi rencana Allah. Realitas perceraian adalah konsesi yang menyakitkan dalam dunia yang retak karena dosa.
Sebagaimana Allah Trinitas yang saling mengasihi tanpa terpisah dan tanpa melebur, demikian pula suami dan istri dipanggil untuk hidup dalam kesatuan kasih yang tidak meniadakan keunikan masing-masing. Bayangkan sosok pribadi Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan Tiga Pribadi Ilahi yang berbeda, namun satu (esa) dalam esensi (hakikat). Mereka tidak saling menelan, tidak saling menghapus/menyingkirkan, tetapi saling menghidupi dalam tarian kasih yang kekal. Inilah yang disebut para bapa gereja sebagai perichoresis, yaitu istilah Yunani yang menggambarkan mutual indwelling, berkelindan, dan saling tinggal di dalam yang lain.
Jürgen Moltmann, dalam The Trinity and the Kingdom (1981), mengembangkan teologi sosial Trinitas (social Trinity) yang menekankan bahwa Trinitas bukan monarki tunggal dengan subordinasi, melainkan komunitas kasih yang setara. Inilah model bagi perkawinan yang sesungguhnya, yaitu suami dan istri tidak menjadi seragam, melainkan saling melengkapi; tidak menindas, melainkan menghidupi kasih yang membebaskan.
Relasi mereka mencerminkan kasih Allah Trinitas, yaitu kasih yang saling memberi ruang, saling menghidupkan, dan saling menopang. Miroslav Volf, dalam After Our Likeness (1998), memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa gereja (dapat kita tambahkan, keluarga) dipanggil untuk menjadi ikon Trinitas (imago Trinitatis). Bukan hanya individu yang diciptakan menurut gambar Allah, tetapi relasi itu sendiri yang mencerminkan kedirian Allah. Stanley Grenz, dalam The Social God and the Relational Self (2001), menulis dengan indah, “Kita menemukan identitas kita bukan dalam isolasi, melainkan dalam relasi.” Keluarga Kristen adalah tempat di mana identitas itu dibentuk, bukan melalui dominasi atau penyeragaman kedua insan, melainkan melalui kasih yang memberi ruang bagi perbedaan.
Dalam terang kasih Trinitas itu pula, suami dan istri dipanggil untuk membangun relasi yang setara, bukan hierarkis. Tidak ada tempat bagi dominasi atau diskriminasi gender di dalam keluarga Kristen yang sejati. Istri bukan “kanca wingking”—istilah Jawa yang merendahkan perempuan sebagai “teman di belakang” yang hanya mengurus dapur dan kasur. Istri bukan bayang-bayang suami yang tidak memiliki suara, melainkan “penolong sepadan” (ezer kenegdo—Kejadian 2:18) yang bersama-sama mencerminkan kemuliaan dan kasih Allah.
Surat Galatia 3:28 menyatakan dengan jelas, “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.” Ini bukan berarti meniadakan perbedaan biologis atau peran yang saling melengkapi, melainkan menegaskan bahwa dalam Kristus, tidak ada hierarki nilai. Rebecca Merrill Groothuis, dalam Good News for Women (1997), menekankan bahwa Injil adalah kabar baik pembebasan, yaitu pembebasan dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan gender. Sementara pandangan komplementarian seperti yang dikemukakan Wayne Grudem dan John Piper dalam Recovering Biblical Manhood and Womanhood (1991) menekankan perbedaan peran, kita harus sangat hati-hati agar perbedaan peran tidak menjadi dalih bagi ketidakadilan.
Gilbert Bilezikian, dalam Community 101 (1997), menerapkan prinsip perichoresis pada relasi komunitas, yaitu kasih sejati selalu menciptakan ruang bagi yang lain, bukan menelan atau meniadakan yang lain. Dalam kasih Kristus, baik suami maupun istri menemukan martabatnya sebagai pribadi yang dikasihi dan dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat. Kasih tanpa syarat inilah yang menjadi inti dari keluarga kristosentris-trinitaris. Kasih yang tidak menuntut imbalan, tidak bersifat transaksional, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Di zaman yang serba pragmatis ini, di mana setiap relasi diukur dengan logika untung-rugi, kasih semacam ini terdengar naif. Namun inilah kasih agape merupakan kasih yang dinyatakan Kristus ketika Ia mati di kayu salib bagi orang-orang yang tidak layak.
Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4:19 mengingatkan kita, “Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.” Keluarga Kristen adalah keluarga yang telah ditebus oleh darah Kristus; karena itu, mereka dimampukan untuk mengasihi dengan tulus, bahkan ketika harus berkorban. Ini bukan kasih yang bergantung pada perasaan yang naik-turun seperti gelombang laut, melainkan kasih yang berakar pada keputusan kehendak yang diperkuat oleh anugerah Tuhan. C.S. Lewis, dalam The Four Loves (1960), membedakan empat tipe kasih: storge (kasih sayang natural), philia (kasih persahabatan), eros (kasih romantis), dan agape (kasih ilahi yang tanpa syarat). Lewis menulis bahwa agape adalah satu-satunya kasih yang tidak bisa rusak, karena ia tidak bergantung pada nilai objek yang dicintai, melainkan pada karakter subjek yang mencintai. Inilah kasih yang dipanggil untuk hidup dalam keluarga Kristen, yaitu kasih yang mencintai bukan karena yang dicintai sempurna, melainkan karena yang mencintai telah dipenuhi oleh kasih Allah.
Søren Kierkegaard, dalam Works of Love (1847), menulis dengan tajam bahwa kasih Kristen adalah tugas (duty), maksudnya kasih bukan dalam pengertian beban yang menjemukan, melainkan dalam pengertian panggilan mulia yang memerdekakan. Kasih sejati adalah kasih yang memilih untuk mengasihi, ketika perasaan tidak mendukung, bahkan ketika yang dicintai tidak layak. Dalam kasih yang telah ditebus oleh Kristus itu, suami dan istri dipanggil untuk saling menghormati dan memelihara kekudusan hidup mereka. Efesus 5:25 memerintahkan suami-suami, yaitu “Kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya.” Ini adalah standar yang tinggi, bukan sekadar mencintai ketika nyaman, melainkan mencintai hingga rela mati berkorban.
Perselingkuhan, dalam bentuk apapun, tidak memiliki tempat di dalam kasih yang kudus. Ibrani 13:4 menegaskan, “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.” Tuhan Yesus menegaskan dengan lebih tajam lagi dalam Matius 5:28, yaitu “Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.” Lewis B. Smedes, dalam Sex for Christians (1994), menulis bahwa seksualitas Kristen bukan tentang represi, melainkan tentang ekspresi kasih yang kudus dan eksklusif. Kesetiaan dimulai dari hati yang murni, yaitu dari tekad untuk menolak keinginan yang menodai kasih sejati. Christopher West, dalam Theology of the Body for Beginners (2004), mempopulerkan pemikiran Paus Yohanes Paulus II bahwa tubuh manusia dirancang Allah untuk menjadi bahasa kasih, yaitu bahasa yang hanya bisa dimengerti dalam konteks komitmen mencintai seumur hidup.
Kesetiaan bukanlah beban yang membatasi kebebasan, melainkan benteng yang melindungi kasih dari pengkhianatan. Karena itu Gary Chapman, dalam The Five Love Languages (1992), mengajarkan bahwa kasih perlu diekspresikan dalam bahasa yang menguatkan pasangan, yaitu melalui kata-kata affirming (peneguhan) quality time (waktu yang berkualitas), pemberian hadiah, tindakan melayani, atau sentuhan fisik. Namun apapun bahasanya, kasih sejati selalu berbicara dalam dialek kesetiaan.
Relasi keluarga Kristen berakar dalam ketaatan pada firman Tuhan. Makna Firman bukan hanya bacaan rohani yang dipaksakan seperti obat pahit yang harus ditelan, tetapi makanan rohani setiap hari, seperti roti yang menghidupi, dan air yang menyegarkan. Mazmur 119:105 menyatakan secara puitis, yaitu: “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” Sebagaimana yang ditulis Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3:16, “Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.” Dengan membaca dan merenungkan firman setiap hari, keluarga Kristen terus-menerus belajar menata langkah, memecahkan persoalan, dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan.
Eugene Peterson, dalam Eat This Book (2006), menggunakan metafora. Ia menggambarkan bahwa membaca Alkitab bukan seperti kita membaca manual instruksi atau koran pagi, melainkan seperti memakan roti yang harus diserap, dan dicerna, agar menjadi bagian dari tubuh kita. Firman Tuhan bukan hanya informasi untuk otak, melainkan formasi untuk jiwa. Dallas Willard, dalam The Spirit of the Disciplines (1988), menekankan bahwa disiplin rohani seperti membaca Alkitab bukanlah cara untuk mendapatkan poin di hadapan Tuhan, melainkan sarana anugerah (means of grace) di mana Tuhan membentuk karakter kita. Richard Foster, dalam Celebration of Discipline (1978), menulis bahwa disiplin rohani adalah jalan menuju kebebasan, yaitu kebebasan dari perbudakan dosa, dan kebebasan untuk menjadi manusia yang penuh (well-being).
Firman Tuhan dalam Yosua 1:8 memberikan janji yang indah, “Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.” Ini bukan formula magis untuk kesuksesan material, melainkan janji bahwa hidup yang dibangun di atas firman Tuhan akan berdiri kokoh. Dari dasar itulah, keluarga Kristen menanamkan nilai rohani kepada anak-anak mereka. Sejak dini mereka telah diajar mengenal firman Tuhan sebagaimana dipraktikkan umat Israel dalam tradisi Shema.
Ulangan 6:7-9 memerintahkan, “Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” Firman Tuhan menjadi isi percakapan di rumah. Ia menjadi napas dialog antara suami, istri, dan anak-anak. Di sini bukan percakapan formal yang kaku di meja makan setelah doa syukur, melainkan percakapan spontan yang mengalir, yaitu ketika anak bertanya tentang ketidakadilan di sekolah, saat remaja bingung tentang arti hidup, atau manakala para dewasa muda menghadapi pilihan karir.
Namun, pengajaran firman bukanlah bentuk indoktrinasi yang kaku. Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), mengkritik apa yang ia sebut “banking model” yaitu model pendidikan di mana guru memasukkan pengetahuan ke dalam kepala murid yang dianggap kosong. Model ini menciptakan manusia-manusia yang pasif, yang tidak mampu berpikir kritis. Keluarga Kristen dipanggil untuk mendidik anak-anak bukan dengan doktrinisasi, melainkan dengan dialog yang hidup dan terbuka. Anak-anak tidak dididik untuk menjadi sikap fanatik yang menghakimi siapa saja yang berbeda, tetapi untuk memiliki hati yang terbuka, kritis, dan rendah hati di hadapan kebenaran Allah.
Tedd Tripp, dalam Shepherding a Child’s Heart (1995), menekankan pendekatan gospel-centered dalam mendidik anak. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan bukanlah menciptakan anak-anak yang patuh secara eksternal karena takut hukuman, melainkan membentuk hati yang mencintai Allah dan sesama. Marva Dawn, dalam Is It a Lost Cause? Having the Heart of God for the Church’s Children (1997), mengajak gereja dan keluarga untuk tidak menyerah pada kecenderungan dan kesenangan generasi muda, melainkan membimbing mereka dengan kasih yang sabar dan mendidik.
James Fowler, dalam Stages of Faith (1981), mengingatkan kita bahwa iman berkembang melalui tahapan-tahapan (proses bertumbuh). Iman anak tidak sama dengan iman remaja, dan iman remaja tidak sama dengan iman dewasa. Karena itu, mendidik anak dalam iman memerlukan kebijaksanaan untuk menyesuaikan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Firman Tuhan dalam Kolose 3:16 memberi nasihat, yaitu: “Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur satu sama lain…” Ini adalah visi komunitas belajar yang mutual di mana orang tua mengajar anak, tetapi juga belajar dari anak. Dengan demikian, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang mampu menghargai perbedaan, tanpa kehilangan iman yang teguh. Catherine Stonehouse dan Scottie May, dalam Listening to Children on the Spiritual Journey (2010), menekankan pentingnya mendengarkan secara empatis anak-anak. Terlalu sering orang dewasa hanya berbicara kepada anak-anak, tetapi tidak mau mendengarkan pergumulan spiritual mereka yang sesungguhnya. Padahal dalam mendengarkan itulah, dialog sejati terjadi.
Buah dari kehidupan yang berakar dalam iman kristosentris-trinitaris adalah tindakan nyata dalam kasih. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3:17, “Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.” Keluarga Kristen dipanggil untuk memancarkan kasih melalui perbuatan baik kepada sesama bukan hanya kepada yang seiman, tetapi kepada semua orang. Efesus 2:10 menegaskan, “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya.” Kita diciptakan bukan untuk hidup bagi diri sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus dalam Matius 5:16 mengajak, “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.”
N.T. Wright, dalam After You Believe: Why Christian Character Matters (2010), menulis bahwa kehidupan Kristen bukan hanya tentang percaya yang benar (orthodoxy) atau merasa yang benar (orthopathy), melainkan tentang bertindak yang benar (orthopraxy). Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati (Yak. 2:26). James K.A. Smith, dalam You Are What You Love (2016), menekankan bahwa kita dibentuk oleh praktik dan kebiasaan kita. Karakter Kristen tidak terbentuk hanya melalui pengetahuan kognitif, melainkan melalui kebiasaan mengasihi dalam tindakan nyata.
Keluarga Kristen secara mendasar menolak segala bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik di tengah lingkungan sekitarnya. Efesus 4:31-32 memerintahkan, “Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.” Kolose 3:19 secara khusus mengingatkan suami, “Hai suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.” Catherine Clark Kroeger dan Nancy Nason-Clark, dalam No Place for Abuse (2001), mengekspos realitas menyedihkan bahwa kekerasan domestik juga terjadi di keluarga-keluarga Kristen. Mereka menekankan bahwa tidak ada teologi atau tafsir Alkitab yang membenarkan kekerasan dengan alasan apapun.
Luka dan trauma masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk melukai kembali. Terlalu sering kita mendengar pembelaan, misalnya: “Saya dipukul orang tua saya dulu, jadi wajar kalau saya memukul anak saya.” Atau: “Saya dikhianati dulu, jadi saya tidak bisa mempercayai siapa pun lagi.” Namun keluarga Kristen dipanggil untuk memutus siklus kekerasan dan luka. Dalam Kristus, segala luka telah disembuhkan, yang retak dipulihkan, dan setiap hati dimerdekakan oleh kasih yang mengampuni. Yesaya 61:1 bernubuat tentang misi Mesias, yaitu: “Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara.”
Jadi, ciri sejati keluarga Kristen bukanlah kesempurnaan tanpa cela seperti foto-foto keluarga bahagia di media sosial misalnya Instagram yang seringkali menyembunyikan pergumulan di balik layar. Ciri sejati keluarga Kristen adalah kemampuan untuk terus mengampuni. Matius 18:21-22 mencatat dialog yang menyentuh hati antara Petrus dan Yesus. Petrus bertanya dengan bangga, seakan-akan ia sudah sangat murah hati, “Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?” Dan Yesus menjawab dengan jawaban yang meruntuhkan perhitungan manusiawi: “Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.”
Makna tujuh puluh kali tujuh itu bukan angka literal yang harus dihitung dengan teliti. Pengampunan sejati tidak menghitung berapa kali kita sudah memaafkan. Pengampunan sejati adalah disposisi hati yang terus-menerus memilih untuk melepaskan kepahitan. L. Gregory Jones, dalam Embodying Forgiveness (1995), menulis bahwa pengampunan Kristen bukan sekadar perasaan psikologis atau teknik manajemen konflik. Pengampunan adalah praktik teologis yang berakar pada karya penebusan Kristus. Kita bisa mengampuni bukan karena luka yang kita alami tidak menyakitkan, melainkan karena kita telah menerima pengampunan yang jauh lebih besar dari Allah.
Kolose 3:13 mengingatkan, “Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun harus berbuat demikian.” Miroslav Volf, dalam Exclusion and Embrace (1996), menulis dari pengalaman pribadinya sebagai orang Kroasia yang telah menyaksikan kekejaman perang. Ia menulis bahwa pengampunan bukan tentang melupakan atau meminimalkan kejahatan yang terjadi, melainkan tentang kesadaran melepaskan keinginan untuk membalas dendam dan membuka ruang bagi rekonsiliasi. Desmond Tutu, dalam No Future without Forgiveness (1999), merefleksikan pengalamannya. Dalam Truth and Reconciliation Commission, Tutu di Afrika Selatan pasca-apartheid, ia menulis bahwa pengampunan adalah satu-satunya jalan menuju masa depan.
Tanpa pengampunan, masyarakat dan keluarga akan terus terjebak dalam siklus balas dendam yang tidak pernah berakhir. Karena itu surat Roma 12:21 mengajarkan prinsip yang revolusioner, “Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!” Ini bukan sikap naif yang menutup mata terhadap realitas kejahatan. Ini adalah strategi rohani yang mengakui bahwa kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan yang lebih besar, melainkan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan yang lebih besar, yaitu kebaikan yang bersumber dari Allah.
Mereka telah belajar memaafkan sebagaimana Allah telah mengampuni mereka di dalam Kristus. Di sanalah kasih sejati bertumbuh, yaitu kasih yang memulihkan, menghidupkan, dan meneguhkan iman seluruh anggota keluarga untuk terus berjalan bersama dalam terang kasih Allah Trinitas yang kekal.
Dengan demikian keluarga kristosentris-trinitaris bukan sekadar unit sosial yang hidup berdampingan untuk kepentingan bersama. Keluarga Kristen merupakan ikon Trinitas, yaitu gambaran hidup tentang kasih Allah yang saling memberi ruang, saling menghidupi, dan saling menopang. Ketika dunia di luar sana lebih dipenuhi dengan relasi transaksional yang menghitung untung-rugi, keluarga Kristen memancarkan kasih yang tanpa syarat. Ketika budaya di sekitar kita meninggikan individualisme dan otonomi mutlak, keluarga Kristen menunjukkan bagaimana keindahan hidup bersama dalam saling ketergantungan yang sehat. Keluarga Kristen secara kreatif mampu menghadirkan cinta-kasih Allah Trinitaris melalui pola relasi, pola asuh, dan pola rohani sebagaimana yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus.
Pdt. Yohanes Bambang Mulyono
 Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi
Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi