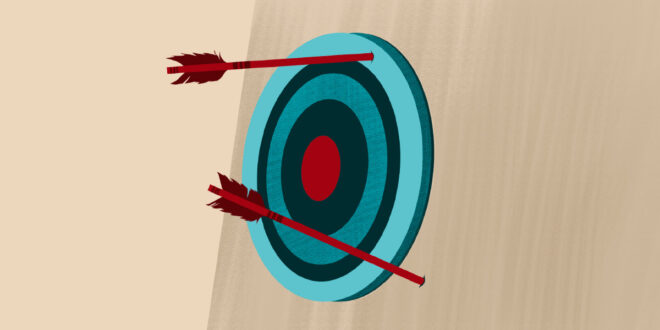Dalam teologi Kristen, ada sebuah ajaran yang selalu menyentuh hati dan menggugah perenungan, yaitu dosa warisan. Ajaran ini membawa kita kembali pada pertanyaan paling mendasar, yaitu siapakah manusia sesungguhnya di hadapan Allah? Apakah manusia pada dasarnya baik, dan bisa diselamatkan semata-mata oleh moralitasnya? Atau, adakah sesuatu yang lebih dalam, lebih rapuh, dan lebih rusak dalam diri kita, yang tak bisa diperbaiki hanya dengan usaha etis? Mengapa kejatuhan satu manusia di Taman Eden bisa mempengaruhi seluruh sejarah umat manusia?
Dosa warisan (dalam tradisi Latin disebut peccatum originale) bukan pertama-tama membahas dosa-dosa konkret yang kita lakukan sehari-hari. Ia justru menunjuk pada kondisi manusia yang sudah “terluka” sejak awal. Yang diwariskan bukan cuma pola perilaku buruk, tetapi lebih pada suatu keadaan: hubungan manusia dengan Allah yang retak, kehendak yang lemah, akal budi yang gelap, serta kerinduan rohani yang kehilangan arah. Manusia tidak lagi hidup dalam keutuhan sebagaimana dirancang Allah, melainkan dalam keberadaan yang sudah menyimpang dari rencana awal-Nya.
Oleh karena itu, penting membedakan dosa warisan dari dosa perbuatan. Dosa perbuatan adalah tindakan nyata yang dengan sadar melanggar kehendak Allah misalnya berbohong, berbuat tidak adil, melakukan kekerasan, atau merusak kesucian hidup. Untuk dosa-dosa seperti ini, setiap orang bertanggung jawab secara pribadi. Seperti ditegaskan Alkitab, “Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya” (Yehezkiel 18:20). Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan Allah selalu adil dan tidak sewenang-wenang.
Namun, dosa warisan bergerak pada lapisan yang jauh lebih dalam. Ia bicara tentang keadaan manusia sebelum ia bertindak. Manusia berdosa bukan hanya karena berbuat dosa, tetapi karena ia hidup dalam kondisi berdosa. Ini bukan sekadar persoalan etika, melainkan soal hakikat keberadaan kita sendiri. Ada perbedaan mendasar antara orang yang sesekali berbuat jahat, dengan manusia yang natur terdalamnya sudah kehilangan orientasi kepada Allah. Di sinilah dosa warisan menyentuh inti identitas kita.
Tradisi teologi klasik, terutama dari Bapa Gereja Augustinus yang kemudian dikembangkan dalam teologi Reformasi, membantu kita memahami kedalaman masalah ini melalui tiga aspek yang saling terkait:
- Culpa: manusia berada dalam status “bersalah” karena solidaritasnya dengan Adam, sebagai wakil umat manusia.
- Corruptio: natur manusia yang rusak, sehingga ia tak mampu, dengan kekuatannya sendiri, mencari Allah atau menghidupi kebaikan sejati.
- Privatio: hilangnya kebenaran asali, yaitu keutuhan relasi dan moral yang dahulu menjadi ciri manusia ciptaan Allah.
Ketiganya bukan konsep yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang menggambarkan betapa dalamnya luka dosa dalam diri manusia.
Kisah kejatuhan di Kejadian 3 bukan sekadar cerita moral tentang dua manusia pertama yang tidak taat. Kisah ini adalah sebuah narasi teologis tentang peristiwa yang bersifat representatif, yaitu sebuah kejatuhan yang dampaknya menjangkau seluruh ciptaan. Adam di sini tidak hanya tampil sebagai individu, melainkan sebagai kepala umat manusia. Tindakannya membawa konsekuensi bagi semua keturunannya. Kejatuhannya mengguncang tatanan dunia dan menandai sejarah manusia sebagai sejarah yang terluka sehingga munculnya sejarah yang menantikan pemulihan.
Namun justru di titik inilah Injil mulai bersuara dengan penuh harapan. Jika kejatuhan Adam merengkuh semua orang, maka anugerah dalam Kristus menjangkau lebih jauh lagi. Seperti yang ditulis Rasul Paulus, “Jadi sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup” (Roma 5:18). Doktrin dosa warisan membuka mata kita pada kedalaman masalah manusia, agar kita juga bisa memahami keagungan kasih karunia Allah yang tidak dangkal, tidak murah, melainkan menyentuh sampai ke akar keberadaan kita.
Pertama, kejatuhan itu merusak relasi paling mendasar: relasi manusia dengan Allah. Dalam Kejadian 3:8 tertulis, “Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu… di antara pohon-pohon.” Sebelumnya, suara Allah adalah sumber sukacita dan persekutuan yang mesra. Kini suara yang sama menjadi alasan untuk takut dan bersembunyi. Yang berubah bukan Allah, melainkan manusia. Hadirat-Nya yang dulu menghidupkan, kini dirasakan sebagai ancaman. Di sini kita lihat jelas: dosa bukan cuma pelanggaran aturan, melainkan keretakan relasi yang mendalam—pergeseran dari kepercayaan menjadi kecurigaan, dari keterbukaan menjadi pelarian.
Kedua, kejatuhan melukai kehendak manusia. Kehendak yang semula seirama dengan kehendak Allah, kini berbelok menuju otonomi yang memberontak. Manusia ingin jadi penentu bagi dirinya sendiri, menetapkan yang baik dan jahat menurut ukurannya sendiri. Ular berkata kepada Hawa, “Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat” (Kejadian 3:5). Sejak saat itu, ada dorongan batin yang terus menarik manusia menjauh dari Allah dan mengarahkan hidupnya pada kepentingan diri. Pemberontakan ini tak selalu tampil kasar; sering ia bersembunyi di balik rasionalisasi yang canggih, religiositas yang tampak saleh, bahkan kesalehan yang dangkal.
Ketiga, kematian masuk sebagai kenyataan yang tak terhindarkan. Peringatan Allah dalam Kejadian 2:17 bukan ancaman kosong: “pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.” Ini adalah hukum yang berlaku: keterpisahan dari Sumber hidup berujung pada kematian. Firman Allah dalam Kejadian 3:19, “Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu,” menegaskan bahwa kematian bukan sekadar peristiwa biologis yang alamiah, melainkan tanda serius bahwa hidup manusia telah tercabut dari kepenuhannya. Sejak kejatuhan, manusia hidup dalam bayang-bayang kefanaan.
Kenyataan universal tentang kondisi manusia yang berdosa ini tidak berhenti pada kisah awal manusia semata. Ia bergema dalam doa, ratapan, dan pengakuan umat Allah sepanjang sejarah. Daud, dalam Mazmur 51, tidak berusaha membenarkan dosanya yang mengerikan, tetapi justru menyingkap akar masalah yang jauh lebih dalam. Ia mengaku, “Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku” (Mazmur 51:7). Bagi Daud, dosa bukanlah sekadar penyimpangan sesaat, melainkan kenyataan yang telah membentuk keberadaannya sejak awal. Pengakuan ini lahir dari kejujuran rohani yang mendalam, yaitu manusia berdosa bukan hanya karena ia berbuat dosa, tetapi karena ia hidup dalam kondisi kejatuhan.
Salomo, dengan segala kebijaksanaannya, mengakui hal serupa: “Siapakah yang dapat berkata: ‘Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari pada dosaku’?” (Amsal 20:9). Tak seorang pun dapat mengklaim kesucian di hadapan Allah. Ayub, yang dikenal saleh dan jujur, pun mengakui dengan rendah hati, “Siapakah yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak!” (Ayub 14:4). Yeremia juga menggambarkan kedalaman masalah ini, “Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?” (Yeremia 17:9).
Landasan teologis yang paling jelas tentang dosa warisan disampaikan oleh Rasul Paulus, khususnya dalam Roma pasal 5. Di sini ia tidak berspekulasi, melainkan membangun argumen yang kokoh, “Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa” (Roma 5:12). Dosa dan maut memasuki sejarah melalui satu orang, dan dampaknya menyebar kepada semua manusia. Kenyataan universal tentang kematian menjadi bukti tak terbantahkan bahwa dosa pun bersifat universal.
Yang khas dari pemikiran rasul Paulus adalah caranya menempatkan Adam dan Kristus sebagai dua figur wakil dalam sejarah keselamatan. Mereka bukan sekadar dua individu, tetapi kepala dari dua kemanusiaan yang berbeda arah. Ia menulis, “Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar” (Roma 5:19). Melalui Adam, manusia masuk dalam solidaritas dosa dan maut. Melalui Kristus, manusia ditarik ke dalam solidaritas kasih karunia dan hidup.
Struktur “sebagaimana… demikian juga” yang digunakan rasul Paulus bukan sekadar retorika yang indah, melainkan kerangka teologis yang menunjukkan bahwa Allah menanggapi kejatuhan manusia dengan cara yang setara, bahkan melampauinya. Rasul Paulus menjelaskan, “Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran itu. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya…” (Roma 5:15). Kasih karunia tidak hanya memulihkan apa yang rusak, tetapi melimpah melebihi kerusakan itu sendiri.
Kedalaman tragedi manusia ini semakin ditegaskan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, “Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini…” (Efesus 2:1–2). Rasul Paulus menggambarkan kondisi manusia tanpa Kristus bukan sebagai orang sakit yang masih bisa sembuh sendiri, melainkan sebagai orang yang mati secara rohani. Istilah ini sangat radikal. Orang yang mati tidak dapat merespons, bergerak, apalagi menghidupkan dirinya sendiri. Dengan demikian, manusia tidak berada dalam posisi netral yang bebas memilih antara Allah dan dosa. Ia telah terikat dan diperbudak oleh kecenderungan yang terus menariknya menjauh dari Allah. Yesus sendiri menegaskan hal ini, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa” (Yohanes 8:34).
Jika keselamatan sungguh terjadi, itu bukan karena inisiatif atau jasa manusia, melainkan karena Allah sendiri yang lebih dahulu bertindak dengan kasih-Nya. Rasul Paulus menegaskan, “Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita” (Efesus 2:4–5). Allah yang membangkitkan, memanggil kita keluar dari kematian rohani, dan memulihkan relasi yang telah lama rusak.
Dari pemahaman Alkitab yang jujur dan menyeluruh inilah muncul beberapa hal penting yang tidak dapat diabaikan gereja. Doktrin dosa warisan bukan sekadar konstruksi dogmatis yang abstrak, melainkan sebuah “kacamata” yang membantu gereja melihat realitas manusia dengan jernih dan melayani dengan lebih setia.
Pertama, dalam tradisi gereja Reformasi disebut sebagai “kerusakan total”. Istilah ini sering disalahpahami, seolah-olah manusia selalu bertindak sejahat mungkin atau sama sekali tidak mampu berbuat baik. Pemahaman seperti itu keliru. Yang dimaksud “total” adalah bahwa dosa telah menjangkau seluruh aspek keberadaan manusia sehingga tidak ada satu dimensi pun yang tetap utuh, yaitu pikiran, kehendak, emosi, tubuh, relasi sosial, maupun kehidupan rohaninya. Seperti kata Rasul Paulus, “Tidak ada yang benar, seorangpun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah” (Roma 3:10–11). Akal budi tak lagi jernih, kehendak kehilangan kebebasannya yang sejati, perasaan mudah terdistorsi, dan relasi antar manusia menjadi rapuh. Manusia masih dapat berbuat baik dalam arti relatif, tetapi kebaikan itu tidak lagi murni dan tidak mengalir dari relasi yang benar dengan Allah.
Kedua, hal yang menyentuh jantung persoalan keselamatan adalah: manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dosa hanya dipahami sebagai perilaku yang menyimpang, maka pendidikan moral, disiplin rohani, atau reformasi sosial mungkin tampak cukup sebagai solusi. Namun Alkitab menyatakan bahwa masalahnya jauh lebih radikal: natur manusia itu sendiri telah rusak. Karena itu, tidak ada kesalehan, moralitas, atau ritual keagamaan yang cukup untuk menjembatani jurang antara manusia dan Allah yang kudus. Rasul Paulus menulis, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, yaitu jangan ada orang yang memegahkan diri” (Efesus 2:8–9). Percakapan Yesus dengan Nikodemus sangat relevan di sini. Kepada seorang pemimpin agama yang saleh dan terdidik, Yesus tidak menawarkan peningkatan spiritual atau perbaikan bertahap, melainkan kelahiran baru yang radikal, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah” (Yohanes 3:3). Yang dibutuhkan bukan renovasi atau perbaikan diri, melainkan regenerasi, yaitu tindakan penciptaan baru yang hanya datang dari Allah sendiri.
Ketiga, doktrin ini menegaskan bahwa keselamatan sepenuhnya bersifat anugerah. Dosa warisan dengan sendirinya meniadakan segala klaim jasa manusia. Jika manusia benar-benar mati secara rohani, tidak ada ruang bagi inisiatif manusia untuk bangkit sendiri. Kehidupan hanya dapat datang dari Allah yang memberi hidup. Kesadaran ini meluluhkan kesombongan rohani dan membawa manusia pada sikap tunduk dan penuh syukur. Dari awal sampai akhir, keselamatan adalah karya Allah yang telah direncanakan oleh Bapa, digenapi oleh Anak, dan diterapkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita.
Oleh karena itu, dosa warisan tidak boleh dipandang sebagai doktrin yang pesimistis atau melumpuhkan. Sebaliknya, ini adalah pengajaran yang jujur, realistis, dan justru penuh pengharapan. Dengan menunjukkan kedalaman luka manusia, doktrin ini justru membuat kedalaman kasih karunia Allah semakin bersinar terang. Semakin kita menyadari ketidakberdayaan kita, semakin kita bersyukur kepada Allah yang berinisiatif mencari, membangkitkan, dan menyelamatkan kita. Rasul Paulus menyatakan, “Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa” (Roma 5:8). Injil tidak dimulai dari optimisme tentang kemampuan manusia, melainkan dari kasih Allah yang tak pernah menyerah bahkan ketika manusia sudah mati dalam dosa.
Struktur pemikiran yang dibangun Paulus sungguh mendalam. Di dalam Adam, manusia jatuh ke dalam dosa dan maut. Namun di dalam Kristus, manusia tidak hanya dipulihkan ke kondisi semula, tetapi bahkan diangkat kepada kehidupan yang melampaui keadaan awal penciptaan. Adam pertama dibentuk dari debu tanah, yang rapuh dan terbatas. Sedangkan Adam terakhir datang dari surga, membawa kehidupan ilahi yang kekal. Adam pertama menerima hidup sebagai pemberian; Adam terakhir menjadi Sumber hidup itu sendiri. Melalui Adam, manusia mewarisi keterpisahan dan kutuk. Melalui Kristus, manusia menerima persekutuan yang dipulihkan, pembenaran yang sempurna, dan pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Injil tidak sekadar mengembalikan manusia ke titik nol, tetapi membawa kita masuk ke dalam kepenuhan rencana Allah yang mulia.
Di sinilah dosa warisan menyingkapkan kebutuhan terdalam manusia akan Kristus. Doktrin ini menjelaskan mengapa masalah manusia tidak dapat diselesaikan dengan moralitas yang tinggi, agama yang taat, atau kebijaksanaan manusia belaka. Injil kemudian menjawab kebutuhan itu dengan kasih karunia yang radikal. Allah tidak sekadar menambal kerusakan manusia. Ia melakukan tindakan penyelamatan yang menyentuh sampai ke akar keberadaan kita. Tanpa pemahaman akan kedalaman luka akibat dosa warisan, salib mudah direduksi menjadi sekadar simbol pengorbanan atau teladan kasih. Namun, ketika kita menyadari bahwa manusia hidup dalam keadaan berdosa bukan hanya melakukan dosa; bahwa kita mewarisi natur yang rusak, bukan sekadar kesalahan moral; bahwa yang kita butuhkan bukan hanya pengampunan, melainkan penciptaan ulang, maka salib tampil sebagai kebutuhan mutlak. Yesus berkata, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6). Kristus bukan sekadar alternatif keselamatan. Ia adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal.
Pada titik inilah, doktrin dosa warisan membawa kita kepada sikap yang sangat mendasar dalam iman Kristen: ketergantungan total pada kasih karunia Allah. Doktrin ini meruntuhkan setiap bentuk kesombongan rohani dan menggantikannya dengan kepercayaan yang rendah hati. Ia mematahkan ilusi kemandirian spiritual dan mengarahkan kita untuk bersandar sepenuhnya pada karya Allah. Dalam terang ini, iman bukan lagi prestasi yang kita capai, melainkan respons syukur terhadap anugerah yang lebih dahulu bekerja dalam hidup kita.
Lebih dari itu, doktrin ini menuntun kita masuk ke dalam pengalaman Injil yang sangat personal. Allah tidak menunggu manusia menjadi layak terlebih dahulu. Ketika kita masih berdosa, masih terasing, masih tidak berdaya, Allah sudah bertindak lebih dulu dengan penuh kasih. Firman-Nya berkata, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yohanes 3:16).
`Di sinilah paradoks yang indah dari teologi Kristen tersingkap dengan jelas. Pengakuan yang paling jujur tentang kerusakan manusia justru membuka jalan bagi perayaan yang paling agung tentang kasih karunia Allah. Semakin dalam kita menyadari kerapuhan dan keterbatasan kita, semakin terang kemuliaan Kristus bersinar dalam hidup kita. Dan semakin kita bersandar pada kasih karunia-Nya, semakin kita mengalami kehidupan baru yang dianugerahkan oleh Dia yang adalah Adam terakhir, Sumber hidup yang sejati, Penebus yang setia, dan Kepenuhan manusia sejati. Rasul Paulus menegaskan, “Tetapi syukur kepada Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam arak-arakan kemenangan-Nya dan yang menyatakan bau pengenalan akan Dia di mana-mana oleh kami” (2 Korintus 2:14).
Pertanyaan untuk Diskusi
- Apakah adil jika dosa Adam berdampak pada semua manusia?
- Bagaimana keselamatan bayi dan anak yang meninggal?
- Jika semua manusia berdosa, mengapa ada orang yang tampak lebih baik?
- Jika kehendak manusia terikat dosa, mengapa masih bertanggung jawab?
- Apakah dosa warisan tetap benar jika Adam tidak dipahami secara historis?
- Bagaimana dosa Adam diwariskan kepada manusia?
- Jika keselamatan oleh anugerah, apakah manusia masih perlu merespons?
- Mengapa alam dan makhluk lain ikut menderita akibat dosa manusia?
- Apakah semua gereja memahami dosa warisan dengan cara yang sama?
- Jika manusia rusak total, mengapa tetap harus hidup kudus?
Pdt. Em. Yohanes Bambang Mulyono
 Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi
Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi