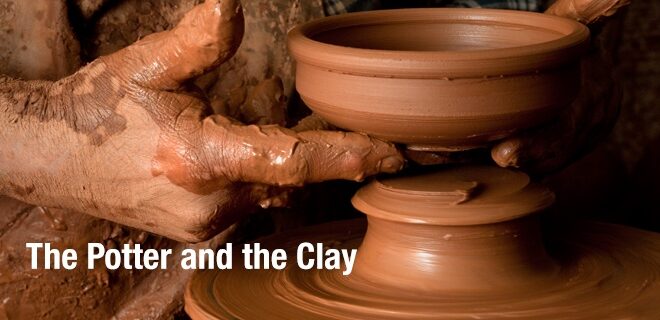Perikop surat Roma 9:19-29 menghadirkan sebuah teka-teki teologis yang telah memikat dan menantang pemikir Kristen selama berabad-abad, yaitu bagaimana mungkin Allah yang berdaulat penuh dapat berdampingan dengan kehendak bebas manusia? Rasul Paulus menggunakan metafora yang kuat—Allah sebagai pembuat tembikar dan manusia sebagai tanah liat—untuk menggambarkan kuasa kreatif Ilahi yang tak terbatas. Dari bahan mentah yang sama, sang Pencipta dapat menghasilkan wadah untuk keperluan istimewa atau penggunaan sehari-hari.
Gambaran ini langsung membawa kita pada pergumulan seputar takdir ilahi, yaitu konsep bahwa Tuhan telah merancang blueprint keselamatan jauh sebelum tindakan manusia pertama terjadi. Namun, Rasul Paulus tidak sedang melukiskan sosok Penguasa yang tiranik atau otoriter. Tujuannya justru mengungkapkan kebaikan hati Ilahi yang melampaui kapasitas nalar kita. Penetapan ilahi yang ia bicarakan bukanlah keputusan ilahi yang tanpa empati, melainkan ekspresi dari komitmen Allah yang tidak pernah ingkar pada perjanjian-Nya.
Pemilihan Allah terhadap manusia tidak didasarkan pada jasa atau prestasi kita, tetapi murni bersumber dari belas kasihan-Nya yang melimpah. Karena itu, penetapan ilahi tidak menghapus tanggungjawab moral manusia; sebaliknya, ia meneguhkan bahwa penyelamatan jiwa adalah inisiatif dan karya Tuhan sepenuhnya.
Meski demikian, pasal yang sama juga mengakui realitas kehendak bebas manusia. Kita tidak sekadar boneka atau robot. Manusia memiliki kapasitas untuk memberikan tanggapan terhadap undangan ilahi. Rasul Paulus mengingatkan kita pada kisah Firaun dalam kitab Keluaran—tokoh yang hatinya mengeras. Namun pengerasan hati Firaun ini bukan semata-mata tindakan sepihak dari Allah; ada peran aktif dari Firaun sendiri yang secara konsisten menolak kebenaran yang ditawarkan kepadanya.
Di sinilah kebebasan manusia menjadi nyata, yaitu kita dapat memilih untuk lentur dan membiarkan diri kita dibentuk, atau kita dapat menolak dan menjadi keras kepala. Ketika Alkitab mencatat bahwa “Allah mengeraskan hati Firaun,” pemahaman yang lebih tepat adalah bahwa Allah membiarkan pilihan-pilihan Firaun mencapai konsekuensi logisnya. Ibaratnya seperti sinar matahari yang sama. Sinar matahari dapat melumerkan lilin namun juga dapat mengeringkan dan mengeraskan tanah. Firman Tuhan juga dapat menghasilkan dampak yang berbeda bergantung pada kondisi hati yang menerimanya.
Dengan demikian, penetapan ilahi dan kebebasan manusia bukanlah dua kutub yang saling membatalkan. Keduanya hidup berdampingan dalam sebuah tegangan yang penuh misteri. Allah adalah sang Pembuat, namun tanah liat yang keras kepala akhirnya akan retak karena kekerasannya sendiri.
Konsep pemilihan yang ditegaskan rasul Paulus dalam ayat 25-26 mengungkapkan sesuatu yang revolusioner, yaitu kasih Allah menembus dan melampaui batasan-batasan etnis, warisan budaya, atau pencapaian manusiawi. Mereka yang dahulu berada di luar lingkaran kini disambut sebagai “umat-Ku.” Mereka yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi syarat kini dipanggil “kesayangan-Ku.”
Rasul Paulus mengutip nubuatan Hosea yang awalnya berbicara tentang “restorasi” Israel pasca-penghukuman, namun ia memperlebar cakupan maknanya untuk merangkul bangsa-bangsa non-Israel. Allah tidak hanya membarui yang tersesat, tetapi juga memanggil mereka yang tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian sebelumnya. Ini adalah manifestasi kasih yang tidak terbatas dan tidak dapat dikalkulasi dengan logika manusia.
Pemilihan Allah bersifat membuka pintu, bukan menutupnya. Ia meruntuhkan klaim-klaim eksklusivitas dan menciptakan ruang bagi siapa pun yang merespons panggilan kasih tersebut. Dalam cahaya Injil Kristus, pemilihan Allah bukan untuk mengangkat segelintir elite rohani, melainkan untuk mengungkapkan rahmat yang menjangkau setiap bangsa di bumi.
Ketegangan antara penetapan ilahi, pemilihan, dan kebebasan ini memiliki implikasi pastoral yang signifikan dan telah melahirkan berbagai perspektif dalam tradisi Kristen.
Dalam lingkaran gereja-gereja Reformatoris, teks ini sering dijadikan landasan untuk menegaskan supremasi mutlak Allah dalam proses penyelamatan—prinsip sola gratia. Johanes Calvin, misalnya, menekankan bahwa keselamatan sepenuhnya bergantung pada keputusan Allah yang tidak dapat dibatalkan, terlepas dari perbuatan baik manusia.
Sementara itu, tradisi teologi Katolik dan Ortodoks menekankan konsep sinergi, yaitu kasih karunia Ilahi senantiasa berkolaborasi dengan kebebasan manusia. Dalam kerangka ini, “penetapan ilahi” dipahami sebagai pengetahuan sempurna Allah tentang bagaimana manusia akan merespons kasih karunia-Nya secara bebas, bukan sebagai determinisme (takdir) yang menghilangkan pilihan manusia.
Arminianisme, yang muncul sebagai alternatif terhadap Calvinisme yang kaku, berpendapat bahwa meskipun Allah memilih, dasar pemilihan-Nya adalah pengetahuan-Nya tentang siapa yang akan beriman. Dalam pandangan ini, kasih karunia Allah mendahului iman manusia, namun manusia tetap memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak tawaran tersebut.
Dalam praktik kehidupan sehari-hari, ketegangan teologis ini tidak perlu dipandang sebagai dilema yang menakutkan. Sebaliknya, ia adalah undangan untuk hidup dengan kerendahan hati. Kita tidak dapat mengendalikan segala aspek keberadaan diri kita, tetapi kita dipanggil untuk merespons kasih Ilahi dengan iman, pengharapan, dan kasih.
Dalam konteks Indonesia yang beragam, ajaran ini membawa makna ganda, yaitu penghiburan dan tantangan sekaligus, yaitu:
Penghiburan, karena kehidupan kita tidak bertumpu pada kekuatan diri sendiri, melainkan berada dalam genggaman Allah yang setia. Di tengah gejolak ekonomi, ketidakstabilan politik, dan dinamika sosial, kita dapat bersandar pada keyakinan bahwa rancangan Allah jauh melampaui skema-skema manusia.
Tantangan, karena kebebasan kita bukanlah izin untuk hidup tanpa arah, tetapi kesempatan untuk terus membuka diri agar kita dapat dibentuk menjadi wadah yang mulia. Dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, pemahaman tentang pemilihan Allah yang inklusif dapat membantu umat Kristen untuk tidak bersikap eksklusif atau merasa superior, namun tetap teguh dalam keyakinan sambil menghargai keberagaman. Surat Roma 9:19-29 juga memiliki dimensi eskatologis yang penting. Ketika rasul Paulus menyebut “wadah murka yang dipersiapkan untuk kehancuran” dan “wadah belas kasihan yang dipersiapkan untuk kemuliaan,” ia tidak berbicara tentang nasib final yang tidak dapat diubah, melainkan tentang tujuan akhir yang masih dalam proses pembentukan.
Konsep “sisa yang kudus” menunjukkan bahwa meskipun tidak semua Israel beriman, Allah tetap setia pada janji-Nya. Bahkan dalam penolakan, Allah masih menyediakan ruang untuk pertobatan dan pemulihan. Ini memberikan harapan bahwa narasi keselamatan belum mencapai titik akhirnya, dan pintu kasih karunia tetap terbuka lebar. Surat Roma 9:19-29 mengajarkan bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan dalam ketegangan misteri—antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, antara pemilihan Allah dan respons iman kita. Ketegangan ini melahirkan spiritualitas yang seimbang dengan karakteristik berikut:
- Kerendahan hati: menyadari bahwa penyelamatan adalah hadiah cuma-cuma, bukan hasil kerja keras kita.
- Tanggung jawab: tetap serius dengan pilihan-pilihan moral dan spiritual yang kita buat.
- Pengharapan: mempercayai bahwa Allah terus bekerja bahkan dalam situasi yang tampak tidak mungkin.
- Kasih: mengasihi sesama karena mereka juga adalah objek kasih Allah yang tak terbatas.
Lalu, ada satu hal yang pasti, yaitu kasih karunia Allah selalu melampaui keterbatasan kita. Seperti tanah liat di tangan sang Pembuat, kita dipanggil untuk percaya, menyerahkan diri, dan membiarkan Allah menyempurnakan karya-Nya dalam hidup kita. Ketika proses pembentukan itu selesai, kita akan mendapati bahwa wadah yang rapuh dan berdosa ini telah ditransformasi menjadi ciptaan baru yang memancarkan kemuliaan Kristus.
Akhirnya, Roma 9:19-29 bukan sekadar teks doktrinal yang harus dianalisis secara intelektual, melainkan undangan untuk memasuki misteri kasih Allah yang melampaui pemahaman rasional. Ketika kita berhenti berupaya memecahkan paradoks ini secara logis semata dan mulai mengalaminya secara eksistensial—dengan seluruh hidup kita—kita akan menemukan kedamaian yang melampaui akal budi. Yaitu damai sejahtera yang datang dari mengetahui bahwa kita berada di tangan sang Pembuat yang penuh kasih.
Pdt. Yohanes Bambang Mulyono
 Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi
Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi