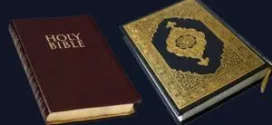Ketika kita membicarakan ajaran Trinitas, yaitu iman bahwa Allah itu esa dalam hakikat namun tiga dalam pribadi sebenarnya kita sedang menyentuh jantung teologi Kristen yang telah membentuk pemahaman iman selama hampir dua ribu tahun. Tapi, bagaimana rumusan ini pertama kali diucapkan dengan tepat? Siapa yang memberikan bahasa untuk menyatakan misteri yang melampaui akal ini? Jawabannya membawa kita pada seorang ahli hukum Romawi dari Kartago bernama Tertulianus, yang hidup pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Masehi. Tertulianus dari Kartago (sekitar 160-220 M) adalah sosok luar biasa dalam sejarah pemikiran Kristen. Dengan latar belakangnya sebagai praktisi hukum Romawi, ia membawa ketajaman hukum dan ketepatan bahasa ke dalam perdebatan teologis yang masih sangat cair pada zamannya.
Lebih dari satu abad sebelum Konsili Nicea melahirkan pengakuan iman yang kita kenal sekarang, Tertulianus sudah merumuskan formula yang menjadi tulang punggung seluruh teologi Trinitas Barat: “Una substantia, tres personae” (satu hakikat, tiga pribadi). Rumusan yang sederhana namun revolusioner ini menjadi bahasa yang memungkinkan gereja berbicara tentang Allah Trinitas dengan kejelasan yang sebelumnya tidak pernah ada.
Untuk memahami betapa pentingnya sumbangan Tertulianus, kita perlu menempatkan diri dalam konteks pergumulan teologis abad ketiga. Pada masa itu, umat Kristen sedang bergulat dengan pertanyaan mendasar: bagaimana kita bisa memahami keilahian Yesus Kristus tanpa mengorbankan kepercayaan pada satu Allah? Bagaimana kita bisa mengakui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah tanpa jatuh ke dalam kepercayaan pada banyak allah? Di tengah pergumulan ini, muncul berbagai jawaban yang berusaha menyelesaikan ketegangan tersebut. Salah satunya adalah modalisme.
Modalisme, yang juga dikenal sebagai Sabelianisme, menawarkan solusi yang tampaknya rapi tapi bermasalah. Ajaran ini mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi tunggal yang menampakkan diri dalam tiga “cara” atau “bentuk” berbeda sesuai dengan fungsi-Nya: Allah sebagai Bapa dalam penciptaan, sebagai Anak dalam penebusan, dan sebagai Roh Kudus dalam pengudusan. Sabelius menggambarkan Allah seperti seorang aktor yang memainkan tiga peran berbeda dalam satu pertunjukan—di satu adegan ia muncul sebagai raja, di adegan lain sebagai pedagang, dan di adegan ketiga sebagai imam. Jadi modalisme melihat Allah sebagai satu pribadi dengan tiga topeng berbeda.
Ajaran tentang Allah sebagai satu pribadi dengan tiga “topeng” (mode) yang berbeda ini disebarkan dengan gencar oleh seorang tokoh bernama Prakseas. Tertulianus menanggapi ajaran Prakseas secara kritis. Salah satu karya teologis Tertulianus yang paling kritis dan berpengaruh berjudul “Adversus Praxean” (Melawan Prakseas). Dalam karya ini, Tertulianus menunjukkan dengan sangat jelas mengapa modalisme adalah ancaman serius bagi iman Kristen yang sejati. Kalau modalisme benar, maka tidak ada percakapan nyata dalam kehidupan ilahi itu sendiri. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, apakah Dia sebenarnya sedang berbicara pada diri-Nya sendiri? Ketika Bapa berkata “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi” saat pembaptisan Yesus, apakah Dia sebenarnya sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri dalam cara yang berbeda? Kejanggalan seperti ini menunjukkan bahwa modalisme, meskipun berusaha melindungi kepercayaan pada satu Allah, justru menghancurkan kenyataan perjumpaan pribadi yang kita lihat dalam Alkitab.
Di sinilah kepiawaian rumusan Tertulianus menolong gereja memahami Allah Trinitas. Dengan menggunakan istilah “substantia” Tertulianus menunjuk pada hakikat atau esensi Allah yang esa, dan “personae” untuk menunjuk pada tiga pribadi Allah yang berbeda. Pemikiran Tertulianus memberikan kerangka yang mempertahankan kedua kebenaran sekaligus: kesatuan mutlak Allah dan perbedaan nyata antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Tertulianus berbicara tentang “una substantia,” ia sedang menegaskan prinsip satu Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalam konteks hukum Romawi, substantia merujuk pada realitas mendasar, sifat hakiki dari sesuatu yaitu “apa yang dimiliki” atau “apa yang membuat sesuatu menjadi apa adanya.” Dengan menggunakan istilah ini dalam bentuk tunggal, Tertulianus menyatakan bahwa apa pun yang merupakan hakikat keilahian, yaitu kekekalan, kemahakuasaan, kemahatahuan, kekudusan, kasih yang sempurna semuanya dimiliki secara penuh dan bersama-sama oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada pembagian atau pemecahan dari hakikat ilahi. Tidak ada tiga allah yang terpisah. Yang ada hanya satu Allah, satu keilahian, satu hakikat ilahi yang tidak terbagi.
Namun, kesatuan hakikat ini tidak berarti keseragaman pribadi. Pribadi Bapa tidak sama dengan pribadi Anak (Kristus), dan pribadi Roh Kudus. Di sinilah Tertulianus memperkenalkan istilah “tres personae” (tiga pribadi). Penggunaan istilah “persona” dalam konteks ini sangat penting dan sering disalahpahami. Banyak pengkritik, baik dari zaman dulu maupun sekarang, mengatakan bahwa dalam konteks teater Yunani-Romawi, “persona” berarti “topeng” atau “peran yang dimainkan,” sehingga penggunaan istilah ini justru mendukung modalisme yang ingin ditolak Tertulianus. Tapi kritik ini mengabaikan latar belakang hukum Tertulianus yang sangat mendasar dalam cara ia menggunakan istilah tersebut.
Dalam hukum Romawi, “persona” punya makna yang khusus dan berbeda dari penggunaan dalam teater. Persona adalah subjek hukum yang mandiri, individu yang punya relasi, hak, dan tanggung jawab. Persona adalah pelaku yang berbeda, bukan sekadar cara tampil atau peran yang dimainkan. Ketika seorang hakim Romawi berbicara tentang dua “personae” dalam sebuah kontrak, ia tidak sedang bicara tentang dua topeng yang dipakai oleh satu orang, melainkan tentang dua pihak yang berbeda yang punya hak dan kewajiban masing-masing. Dengan meminjam ketepatan hukum ini ke dalam teologi, Tertulianus menegaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga subjek yang berbeda, atau tiga “aku” yang punya relasi nyata satu sama lain. Inilah yang membuat rumusan Tertulianus begitu fundamental.
Tertulianus mempertahankan kesatuan mutlak dalam hakikat sambil menegaskan pluralitas nyata dalam kepribadian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mengasihi, dan saling memuliakan. Kondisi relasional ini tidak mungkin terjadi kalau “mereka” hanya cara yang berbeda dari satu pribadi tunggal. Relasi-relasi ini bukan ilusi, bukan sandiwara teologis. Mereka adalah realitas paling mendasar dalam keberadaan Allah itu sendiri. Dalam Adversus Praxean 2, Tertulianus merumuskan perbedaan ini dengan sangat indah: “Mereka bertiga, bukan dalam kondisi tapi dalam tingkatan; bukan dalam hakikat tapi dalam bentuk; bukan dalam kuasa tapi dalam urutan.” Kutipan ini mengandung tiga penegasan kunci yang menunjukkan keseimbangan pemikiran Tertulianus.
Pertama, kesatuan hakiki dalam ketiga Pribadi Allah punya hakikat yang sama, kuasa yang sama, sehingga tidak ada perbedaan hakiki dalam keilahian mereka. Anak bukan “lebih kurang daripada Allah” dibanding Bapa, Roh Kudus bukan “lebih rendah” dari keduanya. Mereka punya keilahian yang identik, penuh, dan tidak terbagi.
Kedua, perbedaan relasional yaitu perbedaan di antara “mereka” terletak pada urutan, tingkatan, dan cara berada. Ini adalah perbedaan pribadi dan relasional, bukan perbedaan dalam keilahian itu sendiri. Bapa adalah sumber yang tidak bersumber, Anak adalah yang diperanakkan, Roh Kudus adalah yang keluar dari Bapa (dan dalam teologi Barat, juga dari Anak). Perbedaan-perbedaan ini menandai identitas pribadi masing-masing tanpa menciptakan hierarki dalam keilahian.
Ketiga, penolakan modalisme. Dengan menekankan bahwa perbedaan ini nyata dan bukan sekadar cara tampil, Tertulianus menolak dengan tegas gagasan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah tiga nama atau tiga cara berbeda untuk berbicara tentang satu pribadi yang sama. Mereka adalah tiga pribadi yang berbeda dalam relasi kekal satu sama lain.
Pencapaian terbesar Tertulianus terletak pada kemampuannya menavigasi antara dua ekstrem yang mengancam kebenaran Trinitas. Di satu sisi ada modalisme yang menyederhanakan Trinitas menjadi satu pribadi dengan tiga topeng, menghancurkan relasi internal dalam Allah sehingga membuat inkarnasi menjadi semacam sandiwara ilahi. Di sisi lain ada “paham tiga allah” (tritheis) yang memisahkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi tiga allah yang berbeda, sehingga menghancurkan monoteisme dan jatuh ke dalam politeisme. Dengan rumusan “una substantia, tres personae,” Tertulianus memberikan jalan tengah yang menjaga kedua kebenaran: kesatuan mutlak dan perbedaan nyata.
Tapi kita harus mengakui bahwa pemikiran Tertulianus, meskipun brilian dan fundamental, tidaklah sempurna. Ada satu aspek dalam teologinya yang perlu diperbaiki, yaitu kecenderungan Tertulianus pada “subordinasianisme ekonomis.” Tertulianus menekankan urutan dalam Trinitas dengan menggunakan serangkaian analogi yang menggambarkan bagaimana Anak “keluar” dari Bapa. Misalnya dalam Adversus Praxean 9, ia menggunakan analogi konsep Trinitas seperti: akar-pohon-buah, sumber-sungai-saluran, dan matahari-sinar-titik cahaya. Pohon keluar dari akar, sungai mengalir dari sumber, sinar keluar dari matahari—demikian pula Anak keluar dari Bapa dan Roh dari keduanya.
Analogi-analogi ini dimaksudkan Tertulianus untuk menunjukkan kesatuan hakikat (sungai punya air yang sama dengan sumber) sambil mempertahankan perbedaan dan urutan relasional. Namun, analogi ini memberi kesan Trinitas Allah bersifat “subordinasionis” karena menyiratkan bahwa Bapa adalah “sumber” yang lebih utama, sementara Anak adalah “derivatif” dari Bapa.
Perlu dicatat bahwa Tertulianus tidak pernah mengajarkan subordinasi ontologis penuh. Tertulianus tidak mengatakan bahwa Anak “inferior” dalam hakikat atau kurang ilahi dibanding Bapa. Subordinasianisme-nya bersifat “ekonomis,” berkaitan dengan urutan dan fungsi dalam karya keselamatan, namun bukan dengan esensi keilahian. Tapi istilah atau ungkapan yang ia gunakan tidak selalu cukup jelas untuk membedakan kedua hal ini. Ternyata ambiguitas ini akan menjadi sumber perdebatan dalam abad-abad berikutnya.
Perlu dipahami bahwa Tertulianus bekerja dalam konteks abad ketiga, lebih dari seabad sebelum Konsili Nicea Pertama. Terminologi teologisnya bersifat proto-Trinitas sebagai fondasi, tapi belum dalam bentuk rumusan yang final. Misalnya istilah Latin “substantia” yang ia gunakan punya konotasi yang sedikit berbeda dari istilah Yunani “ousia” yang nanti digunakan dalam Konsili Nicea, yang punya presisi filosofis lebih tinggi dalam tradisi filsafat Aristoteles. Demikian pula, istilah “persona” akan diganti atau diperjelas oleh istilah Yunani “hypostasis” dalam rumusan Kapadokia yang lebih matang.
Pada abad keempat, Bapa-bapa Kapadokia, yaitu Basilius Agung, Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nyssa membangun di atas fondasi yang sudah diletakkan Tertulianus sambil memperbaiki beberapa kelemahan. Konsili Nicea Pertama menegaskan bahwa tidak ada subordinasi dalam hakikat keilahian. Sang Anak adalah “homoousios” (sehakikat) dengan Bapa. Kristus bukan derivatif atau inferior. Nicea Pertama juga mengembangkan konsep “perichoresis” (saling penetrasi atau saling mendiami), yaitu ketiga Pribadi Allah saling mendiami satu sama lain tanpa kehilangan identitas pribadi masing-masing. Sang Bapa sepenuhnya ada dalam diri Anak, Sang Anak sepenuhnya ada dalam diri Roh Kudus, dan seterusnya. Ketiga pribadi Allah berada dalam semacam tarian ilahi yang kekal. Konsep ini memberikan model kesatuan yang lebih dinamis dan relasional daripada sekadar “berbagi hakikat yang sama.”
Rumusan “satu ousia, tiga hypostasis” dari Bapa-bapa Kapadokia memberikan kejelasan konseptual teologis yang lebih tepat, karena menghindari potensi kesalahpahaman yang bisa muncul dari terminologi Tertulianus. Tapi perkembangan pemikiran Nicea Pertama ini bukan penolakan terhadap Tertulianus, melainkan penyempurnaan dari premisnya. Tanpa fondasi yang diletakkan Tertulianus, perkembangan teologi Trinitas yang matang mungkin akan memakan waktu jauh lebih lama atau mengambil bentuk yang sangat berbeda.
Warisan Tertulianus dalam sejarah gereja tidak bisa diabaikan. Konsep “homoousios” (sehakikat) yang menjadi inti Pengakuan Iman Nicea adalah perkembangan langsung dari “una substantia” Tertulianus. Rumusan “tiga hypostases dalam satu ousia” yang dihasilkan Konsili Konstantinopel I (381 M) adalah revisi dari “tres personae dalam una substantia.” Teologi Barat, khususnya melalui Agustinus dari Hippo yang hidup satu abad setelah Tertulianus masih menggunakan rumusan Latin “una essentia, tres personae.”
Tertulianus sudah mewariskan pada gereja bahasa konseptual teologis yang memungkinkan diskusi yang lebih presisi tentang misteri Allah Trinitas. Dengan kerangka ini gereja bisa menghindar dari ekstrem modalisme dan “paham tiga allah.” Dari perspektif teologi ortodoks Nicea-Konstantinopel, rumusan Tertulianus benar dalam arah dan substansi, meskipun perlu penyempurnaan. Pemikiran Tertulianus bukan bersifat monistik. Ia juga bukan penganut paham tiga allah. Tertulianus adalah arsitek awal dari teologi Trinitas yang seimbang yang menyatakan bahwa satu Allah dalam tiga Pribadi yang berbeda.
Tapi pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah mengapa kita perlu peduli dengan perdebatan teologis yang terjadi hampir dua ribu tahun lalu? Apa relevansi rumusan Tertulianus bagi kehidupan Kristen masa kini? Jawabannya terletak pada pemahaman bahwa teologi bukan sekadar spekulasi abstrak, melainkan fondasi bagi kehidupan spiritual yang sejati. Cara kita memahami Allah secara langsung akan membentuk cara kita berhubungan dengan-Nya, cara kita memahami diri kita sendiri, dan cara kita hidup dalam komunitas.
Doktrin Trinitas yang dirumuskan dengan cermat oleh Tertulianus akan menjaga kita dari pemahaman yang mereduksi Allah menjadi sesuatu yang kurang dari diri-Nya yang sejati. Modalisme modern masih sangat hidup dalam banyak komunitas Kristen kontemporer, meskipun tidak selalu dengan nama itu, misalnya dalam gereja-gereja Pentakosta. Akibatnya ketika orang Kristen berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus seolah-olah mereka hanya berbeda dalam peran atau fungsi tapi bukan dalam personalitas yang riil. Pemikiran dan penghayatan ini pada dasarnya hanya mengulangi kesalahan Prakseas yang sudah ditolak Tertulianus.
Implikasinya sangat serius. Jikalau Trinitas hanyalah tiga mode tampilan, maka inkarnasi kehilangan esensinya yang mendalam. Yesus bukan sungguh-sungguh “Allah yang menjadi manusia” dalam pengertian penuh, melainkan hanya Allah yang memakai “topeng kemanusiaan” untuk sementara waktu.
Pemahaman Trinitas yang benar, seperti yang dinyatakan oleh Tertulianus, menjaga gereja dari reduksionisme semacam ini. Ketika kita paham bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda dalam relasi kekal satu sama lain, sebenarnya kita sedang memahami bahwa inkarnasi adalah peristiwa yang benar-benar nyata dan mengubah sejarah. Pribadi kedua dari Trinitas mengambil kodrat manusia dan menjadi satu dari kita tanpa kehilangan hakikat-Nya sebagai Allah. Inkarnasi bukan sandiwara, bukan ilusi, bukan topeng sementara. Sebaliknya, Allah yang kekal dalam diri Sang Firman memasuki waktu, yang tak terbatas membatasi diri dalam daging, yang transenden menjadi imanen.
Doktrin Trinitas juga memberikan fondasi bagi pemahaman Kristen tentang relasionalitas sebagai hakikat realitas itu sendiri. Dalam tradisi filosofis Yunani, makna “kesempurnaan” sering dikaitkan dengan kemandirian mutlak, sehingga tidak membutuhkan apa pun atau siapa pun. Tapi Trinitas mengajarkan kita sesuatu yang radikal berbeda. Dalam keilahian Allah itu sendiri, relasi bersifat fundamental. Bapa hanya adalah Bapa dalam relasi-Nya dengan Anak; Anak hanya adalah Anak dalam relasi-Nya dengan Bapa; Roh Kudus adalah Roh yang diutus oleh Bapa dan Anak. Identitas personal tidak ada terpisah dari relasi, karena relasi justru membentuk identitas kedirian kita.
Pemahaman ini punya implikasi yang mendalam bagi antropologi Kristen, Cara kita memahami apa maknanya menjadi manusia. Kalau Allah Trinitas adalah relasi dalam hakikat-Nya yang paling mendasar, maka kita yang diciptakan menurut gambar-Nya juga pada dasarnya adalah makhluk relasional. Individualisme radikal yang sering dominan dalam budaya modern. Gagasan bahwa kita adalah “atom-atom” yang mandiri, sehingga identitas kita terpisah dari relasi kita. Makna kebebasan sebagai otonomi mutlak bertentangan secara fundamental dengan antropologi Trinitas. Kita adalah diri kita yang sejati bukan dalam isolasi, melainkan dalam relasi dengan Allah dan sesama. Identitas diri kita dibentuk, bukan dihancurkan, oleh relasi-relasi yang mengikat keberadaan kita.
Relasi dalam Allah yang Trinitas juga memberikan model bagi kehidupan gereja dan komunitas Kristen. Rasul Paulus berbicara tentang gereja sebagai Tubuh Kristus, di mana ada banyak anggota dengan berbagai karunia tapi satu tubuh, dan satu Roh. Ini bukan sekadar metafora yang indah. Sama seperti dalam Allah Trinitas ada kesatuan mutlak dalam hakikat tapi keragaman dalam personalitas, demikian pula dalam gereja seharusnya ada kesatuan dalam Kristus tapi keragaman dalam karunia, panggilan, dan kontribusi. Kesatuan bukan berarti keseragaman; perbedaan bukan berarti perpecahan.
Dalam konteks dunia yang semakin terpolarisasi di mana kita cenderung melihat perbedaan sebagai ancaman dan kesatuan sebagai konformitas. Model Trinitas menawarkan jalan yang kreatif. Tertulianus menunjukkan bahwa kesatuan yang paling mendalam tidak hanya kompatibel dengan perbedaan yang riil, tapi justru kesatuan itu sendiri merupakan sesuatu yang relasional dan dinamis. Gereja yang sehat bukan gereja yang menghilangkan perbedaan demi kesatuan yang artifisial, juga bukan gereja yang merayakan perbedaan sampai kesatuan runtuh. Gereja yang sehat adalah gereja yang mencerminkan kehidupan Trinitas, yaitu kesatuan yang mendalam dalam kasih sambil merangkul keragaman yang akan saling memperkaya.
Doktrin Trinitas juga memberikan fondasi bagi kehidupan doa dan spiritualitas Kristen. Ketika kita berdoa, kita tidak sedang berbicara ke ruang hampa atau ke prinsip impersonal. Kita sedang memasuki dialog yang sudah berlangsung sejak kekal, yaitu dialog antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa kepada Bapa dalam nama-Nya dengan kuasa Roh Kudus. Ini bukan sekadar formula liturgis, tapi sebagai undangan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi itu sendiri. Roh Kudus yang berdiam dalam kita adalah Roh yang sama yang ada dalam relasi kekal dengan Bapa dan Anak, dan melalui Roh inilah kita bisa memanggil Allah sebagai “Abba, Bapa.”
Pemahaman ini mengubah spiritualitas dari tugas religius menjadi partisipasi dalam kehidupan Allah. Doa bukan sekadar berbicara kepada Allah “di luar sana.” Berdoa kepada Bapa dan Anak adalah Roh Kudus yang berdoa dalam kita, sehingga menyatukan kita dengan Kristus dan berbagi dalam relasi-Nya dengan Bapa. Sakramen bukan sekadar ritual simbolis. Melalui sakramen, kita secara nyata dibawa ke dalam persekutuan Trinitas. Baptisan bukan sekadar inisiasi sosial ke dalam komunitas religius, karena baptisan adalah cara di mana kita “dibaptis ke dalam kematian Kristus” sehingga kita bisa bangkit bersama-Nya dalam kehidupan baru, yaitu kehidupan yang berpartisipasi dalam kehidupan Trinitas itu sendiri.
Dalam konteks dialog antaragama di tengah dunia yang terglobalisasi, pemahaman yang jernih tentang Trinitas membantu kita mengomunikasikan iman Kristen dengan lebih efektif. Sering kali, kritik terhadap doktrin Trinitas dari teman-teman Islam, Yudaisme, atau tradisi lain didasarkan pada kesalahpahaman bahwa Kristen percaya pada tiga allah. Rumusan Tertulianus memberikan kita bahasa yang presisi untuk menjelaskan bahwa iman Kristen adalah monoteistik, yaitu kita percaya pada satu Allah, bukan tiga. Namun, Allah yang satu ini adalah komunitas kasih kekal, bukan tunggal atau soliter.
Dialog yang otentik memerlukan kemampuan untuk mengartikulasikan iman kita sendiri lebih jelas sehingga orang lain memahami makna ajaran gereja dengan benar. Tertulianus sudah memberikan pada kita presisi konseptual teologis yang memungkinkan kita mengatakan dengan jelas apa yang kita percayai dan apa yang tidak kita percayai. Kita tidak percaya pada tiga allah yang terpisah. Kita juga tidak percaya pada satu Allah yang kadang-kadang muncul sebagai Bapa, kadang-kadang sebagai Anak, dan kadang-kadang sebagai Roh Kudus. Kita percaya pada satu Allah yang eksis secara kekal sebagai tiga pribadi dalam relasi kasih yang sempurna, yaitu misteri ilahi yang melampaui pemahaman penuh kita, tapi bukan kontradiksi logis.
Dalam zaman yang ditandai oleh individualisme yang ekstrem dan fragmentasi sosial, pemahaman Trinitas tentang personalitas menawarkan alternatif yang radikal. Budaya kontemporer sering mengajarkan bahwa identitas adalah sesuatu yang kita konstruksi sendiri, terlepas dari relasi kita. Misalnya ungkapan “Temukan dirimu sendiri,” atau: “Jadilah dirimu sendiri,” “Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa kamu.” Semua slogan ini, meskipun mengandung beberapa kebenaran, pada akhirnya didasarkan pada antropologi yang keliru. Mereka mengasumsikan bahwa keberadaan diri yang otentik terpisah dari relasi, bahwa menjadi diri sendiri berarti menjadi mandiri dari pengaruh eksternal.
Model Trinitas menantang asumsi ini secara fundamental. Bapa adalah Sang Bapa hanya dalam relasi dengan Anak. Identitas-Nya sebagai Bapa tidak terpisah dari relasi ini. Tapi Sang Bapa tidak kehilangan diri-Nya dalam relasi ini. Sang Bapa justru adalah diri-Nya yang penuh dalam dan melalui relasi dengan Anak dan Roh Kudus. Demikian pula, kita menjadi diri kita yang paling otentik bukan dengan menarik diri dari relasi, melainkan dengan memasuki relasi-relasi yang sehat dan memberi kehidupan. Identitas Kristen dibentuk dalam sakramen baptisan, yaitu suatu tindakan yang secara fundamental relasional, di mana kita mati terhadap kehidupan lama dan bangkit dalam Kristus. Kita bukan lagi milik diri kita sendiri. Kita adalah milik Kristus dan milik dalam persekutuan-Nya.
Doktrin Trinitas juga memberikan fondasi teologis tentang kasih. Rasul Yohanes menulis dalam suratnya bahwa “Allah adalah kasih” (1 Yoh. 4:8). Ini bukan sekadar pernyataan bahwa Allah mengasihi kita atau bahwa Allah penuh kasih, melainkan pernyataan identitas bahwa hakikat Allah adalah kasih. Tapi bagaimana Allah bisa adalah kasih kalau Dia tunggal (satu secara numerik)? Kasih, menurut definisinya, jikalau bersifat relasional. Kasih memerlukan yang mengasihi dan yang dikasihi. Kalau Allah adalah satu pribadi tunggal yang soliter, maka kasih tidak bisa menjadi hakikat-Nya yang paling fundamental. Tapi dalam Trinitas, kasih adalah hakikat Allah dari kekekalan. Sejak kekal Bapa mengasihi Anak dengan kasih yang sempurna; Anak mengasihi Bapa dengan kasih yang sama; Roh Kudus adalah ikatan kasih yang menyatukan mereka. Allah tidak mulai mengasihi ketika Dia menciptakan. Allah menciptakan karena Dia adalah kasih. Kasih ilahi yang relasional “meluap” dalam tindakan penciptaan. Allah menciptakan makhluk-makhluk untuk berbagi dalam kehidupan kasih yang sudah menjadi realitas dari kekekalan dalam Trinitas.
Pemahaman ini mengubah cara kita memahami tujuan hidup Kristen. Kita tidak diciptakan hanya untuk mematuhi hukum moral atau untuk menjalani ritual religius. Sebaliknya kita diciptakan untuk mengasihi untuk berpartisipasi dalam kehidupan kasih yang adalah Allah Trinitas itu sendiri. Perintah terbesar untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri bukan lagi sekadar kewajiban etis eksternal. Sebaliknya sebagai undangan untuk hidup mengasihi sesuai dengan hakikat kita yang paling dalam sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah Trinitas.
Dalam konteks penderitaan dan kejahatan yang begitu nyata dalam dunia kita, doktrin inkarnasi memberikan respons yang solutif. Jikalau Allah adalah tunggal dan transenden, maka penderitaan manusia tetap menjadi misteri yang tak terjawab. Allah yang mahakuasa dan mahabaik tampaknya acuh tak acuh terhadap penderitaan kita. Tapi doktrin Trinitas memungkinkan kita untuk mengatakan sesuatu yang radikal, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus sudah menderita. Dalam Kristus, Pribadi kedua dari Trinitas mengambil kodrat manusia dan mengalami kedalaman penuh penderitaan manusia. Kristus pernah ditolak, dikhianati, disiksa, ditinggalkan, dan wafat. Salib bukan hanya demonstrasi kasih Allah bagi kita. Karena salib adalah peristiwa dalam kehidupan Allah sendiri. Melalui salib, Sang Bapa ikut menderita dalam penderitaan Anak.
Teolog Jerman Jürgen Moltmann dalam karyanya yang berpengaruh, “The Crucified God,” berpendapat bahwa salib adalah peristiwa Trinitas. Sang Anak menderita kematian dalam kesendirian, sementara Sang Bapa menderita karena kehilangan Anak, dan Roh adalah ikatan kasih yang mempertahankan kesatuan bahkan dalam pemisahan yang tak terkatakan ini. Allah di dalam Kristus bukan sekadar pengamat yang memperhatikan realitas penderitaan kita dari jarak yang aman. Dia sudah memasuki penderitaan itu dari dalam. Ini mengubah seluruh cara kita memahami makna “teodise” yaitu masalah teologis bagaimana merekonsiliasi keberadaan kejahatan dengan Allah yang mahakuasa dan mahabaik. Respons Kristen yang paling mendalam bukanlah argumen filosofis abstrak. Melalui salib, Allah sudah memasuki penderitaan dunia dalam Kristus dan mengalaminya dari dalam. Ketika kita menderita, kita tidak menderita sendirian; kita menderita bersama dengan Kristus yang sudah menderita sebelum kita dan yang terus hadir dalam penderitaan kita melalui Roh Kudus. Lebih dari itu, melalui peristiwa salib yang diikuti oleh kebangkitan, kita punya harapan bahwa penderitaan bukan kata terakhir. Allah yang sudah memasuki kematian juga sudah mengalahkannya dengan kebangkitan Kristus.
Dalam era pascamodern yang skeptis terhadap klaim kebenaran universal dan yang merayakan pluralitas perspektif, model Trinitas menawarkan cara untuk menghargai perbedaan tanpa jatuh ke dalam relativisme. Pascamodernisme sering mengkritik “logosentrisme” yaitu klaim bahwa hanya ada satu kebenaran mutlak. Dalam menanggapi kolonialisme intelektual dan hegemoni budaya, pascamodernisme merayakan “decentering” yaitu penolakan terhadap kebenaran tunggal yang mendominasi. Tapi Trinitas menawarkan model yang lebih radikal, karena kebenaran tidak monosentris (satu pusat) dan bukan pula polisentrisme yang kacau (banyak pusat yang tidak terkait), melainkan sesuatu yang bisa kita sebut “perikoretik-sentris” yaitu tiga pusat yang saling mendiami dalam persatuan yang sempurna. Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing adalah “pusat” dalam pengertian tertentu, tapi mereka eksis dalam saling ketergantungan dan saling penetrasi yang sempurna. Tidak ada hierarki dominasi, tidak ada pusat yang menekan pinggiran, tapi juga tidak ada fragmentasi ke dalam atomisme yang tidak terhubung.
Model ini memberikan visi untuk kehidupan bersama baik dalam gereja maupun dalam masyarakat yang lebih luas di mana perbedaan bisa dihargai tanpa meruntuhkan kesatuan. Di sisi lain, kesatuan tetap terpelihara tanpa menghapuskan perbedaan. Ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multikultural, di mana tantangan besar adalah bagaimana mempertahankan kesatuan nasional sambil menghormati keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Model Trinitas tidak memberikan jawaban politik yang sederhana, tapi memberikan visi teologis yang bisa menginspirasi pencarian kita akan persatuan dalam keragaman.
Doktrin Trinitas juga punya implikasi ekologis yang semakin penting di era krisis iklim dan degradasi lingkungan. Kalau Allah Trinitas adalah persekutuan yang relasional, dan kalau seluruh ciptaan adalah karya kasih Trinitas, maka alam semesta itu sendiri pada dasarnya bersifat relasional. Pandangan dunia modern yang mekanistik yang melihat alam sebagai mesin yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisah, yang bisa dieksploitasi tanpa konsekuensi, adalah asing bagi visi Trinitas. Dalam perspektif Trinitas, seluruh ciptaan adalah jaring relasi yang saling terkait, di mana setiap bagian punya nilainya sendiri dalam relasi dengan keseluruhan.
Lebih jauh lagi, inkarnasi menyatakan bahwa materi itu sendiri sudah dikuduskan. Ketika Sang Logos (Kristus) mengambil “daging” manusia, Allah di dalam Kristus tidak hanya menebus manusia secara individual, melainkan juga melakukan penebusan kosmis. Rasul Paulus menulis dalam Roma 8 bahwa seluruh ciptaan “mengeluh dan menderita sakit melahirkan” sambil menantikan penyataan anak-anak Allah. Eskatologi Kristen bukan upaya untuk melarikan diri dari dunia materi ke surga spiritual yang imaterial. Ini memberikan fondasi teologis untuk tanggung jawab ekologis. Kita dipanggil merawat ciptaan bukan hanya karena itu berguna bagi kita, melainkan karena ciptaan itu sendiri punya martabat dan tujuan dalam rencana ilahi.
Dalam konteks globalisasi dan kapitalisme yang sering mereduksi manusia menjadi unit ekonomis dan mengukur nilai berdasarkan produktivitas, doktrin Trinitas memberikan fondasi untuk martabat manusia yang tidak bergantung pada pencapaian. Jikalau manusia diciptakan menurut gambar Allah Trinitas, maka martabat manusia tidak didasarkan pada apa yang kita produksi atau kontribusi kita kepada ekonomi, melainkan pada fakta bahwa kita diciptakan untuk relasi, untuk kasih, untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Karena itu anak yang cacat, orang tua yang pikun, orang yang tidak produktif secara ekonomis, yaitu semua pihak punya martabat yang tak terbatas bukan karena apa yang bisa mereka lakukan, melainkan karena siapa mereka, yaitu makhluk relasional yang diciptakan menurut gambar Allah relasional.
Ajaran Trinitas memberi implikasi mendalam untuk etika sosial Kristen. Masyarakat yang adil bukan masyarakat di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi produktif dan kompetitif, melainkan masyarakat di mana relasi-relasi yang memberi kehidupan diprioritaskan di atas akumulasi material. Dalam perspektif Trinitas, “kesuksesan” diukur bukan dengan seberapa banyak kita miliki atau seberapa tinggi kita naik dalam hierarki sosial, melainkan dengan seberapa dalam kita berpartisipasi dalam relasi kasih dengan Allah dan dengan sesama.
Doktrin Trinitas juga memberikan fondasi untuk pemahaman Kristen tentang kebebasan yang sangat berbeda dari konsep liberal klasik. Pemikiran liberalisme cenderung mendefinisikan kebebasan sebagai otonomi, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan tanpa hambatan eksternal. Semakin sedikit kita bergantung pada orang lain, semakin bebas kita. Tapi model Trinitas menunjukkan bahwa kebebasan yang sejati bukan otonomi melainkan “otonomi-dalam-persekutuan” yaitu kebebasan yang justru direalisasikan dalam dan melalui relasi. Sang Bapa adalah Allah yang bebas secara sempurna, tapi kebebasan-Nya tidak ada terpisah dari relasi-Nya dengan Anak dan Roh Kudus. Dia bebas untuk mengasihi, bebas untuk memberi diri, bebas untuk ada dalam persekutuan. Makna kebebasan ilahi bukan tentang otonomi, melainkan tentang realisasi diri yang penuh dalam kasih yang memberi diri. Demikian pula kita menjadi bebas bukan ketika kita terlepas dari semua ikatan, melainkan ketika kita terikat dalam kasih, yaitu ketika kita bebas untuk mengasihi, bebas untuk melayani, bebas untuk memberi diri demi kebaikan orang lain.
Dalam konteks perdebatan gender dan seksualitas yang begitu intens dalam budaya kontemporer, Trinitas menawarkan model relasi yang melampaui kategori-kategori yang kita gunakan dalam konteks manusia. Dalam Trinitas, ada perbedaan riil yaitu Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, sebab perbedaan ini tidak menciptakan hierarki yang saling mendominasi. Tidak ada Pribadi yang lebih penting atau lebih berharga dari yang lain. Kesatuan mereka tidak didasarkan pada keseragaman atau penghapusan perbedaan, melainkan pada kasih yang sempurna yang menghormati dan merayakan otherness.
Terhadap budaya patriarki yang menggunakan ungkapan “Bapa” untuk membenarkan dominasi maskulin. Model Trinitas mengingatkan kita bahwa “Bapa” dalam Trinitas tidak mendominasi atau mengendalikan Anak dan Roh Kudus, melainkan eksis dalam relasi kasih yang setara. Ketiga Pribadi punya keilahian yang sama penuh, kuasa yang sama, kemuliaan yang sama. Perbedaan mereka adalah perbedaan relasional, bukan perbedaan nilai atau kuasa.
Warisan terbesar Tertulianus bagi kita bukan sekadar rumusan teologis yang presisi, meskipun itu penting. Warisan terbesarnya adalah undangan untuk memasuki misteri kehidupan Allah Trinitas itu sendiri. Tertulianus memberikan kita bahasa untuk berbicara tentang Allah yang adalah persekutuan kasih yang kekal, tapi tujuan akhir bukan sekadar berbicara tentang Allah. Tujuan akhir adalah berpartisipasi dalam kehidupan Allah, dibawa ke dalam tarian perikoretik Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dalam baptisan, kita dibaptis “dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” yaitu bukan tiga nama, tapi satu nama yang adalah Allah Trinitas. Kita dihisabkan ke dalam kehidupan Trinitas, mati terhadap kehidupan lama yang ditandai oleh keterasingan dan dosa, dan bangkit ke dalam kehidupan baru yang ditandai oleh persekutuan dengan Allah dan sesama. Dalam sakramen Ekaristi (Perjamuan Kudus), kita menerima Tubuh dan Darah Kristus, bersatu dengan Dia. Melalui Kristus, kita bersatu dengan Bapa dalam Roh. Dalam doa, kita memanggil Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh.
Kehidupan Kristen, dalam pengertian yang paling penuh, adalah kehidupan Trinitas. Bukan kehidupan yang kita jalani untuk Allah dari luar, melainkan kehidupan Allah yang kita jalani dari dalam. Kita menjadi, sebagaimana Petrus katakan, “berpartisipasi dalam kodrat ilahi” (2 Ptr. 1:4). Ini bukan peleburan mistis di mana kita kehilangan identitas kita, melainkan penggenapan identitas kita yang paling sejati. Sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing mempertahankan identitas pribadi mereka sambil ada dalam kesatuan yang sempurna, demikian pula kita mempertahankan keunikan kita sebagai individu sambil dibawa ke dalam persekutuan ilahi.
Visi kehidupan manusia sebagai partisipasi dalam kehidupan Allah Trinitas. Dalam arti yang sama teologi Kristen Timur (Orthodoks) menggunakan istilah “teosis” atau “pengilahian.” Athanasius, salah satu pembela utama ortodoksi Nicea, merumuskannya dengan indah, yaitu “Allah menjadi manusia agar manusia bisa menjadi Allah.” Tentu saja ini tidak berarti bahwa kita menjadi Allah dalam pengertian ontologis. Kita tetap makhluk, bukan Pencipta. Tapi melalui rahmat-Nya, kita diangkat untuk berbagi dalam kehidupan Allah, untuk berpartisipasi dalam atribut-atribut ilahi seperti kasih, kekudusan, keabadian (dalam pengertian terbatas kita), dan persekutuan dengan Kristus.
Tertulianus, dengan rumusan “una substantia, tres personae,” memberikan pada gereja alat konseptual untuk memahami dan mengutarakan kebenaran ini. Tanpa kejelasan tentang siapa Allah bahwa Dia adalah satu dalam hakikat tapi tiga dalam pribadi, kita tidak akan punya kejelasan tentang siapa kita dan untuk apa kita dipanggil. Ajaran Trinitas bukan sekadar dogma abstrak yang harus kita percayai tetapi sebagai peta jalan menuju kehidupan yang diberkati, kehidupan yang Allah maksudkan untuk kita sejak awal.
Dalam dunia yang semakin terpecah-pecah, di mana individualisme mengasingkan kita dari satu sama lain, di mana ketidakadilan struktural menciptakan jurang antara yang berkuasa dan yang tertindas, di mana krisis ekologis mengancam masa depan planet kita, di mana relativisme moral membuat kita bingung tentang apa yang benar dan salah. Dalam dunia seperti ini, ajaran Trinitas menawarkan harapan. Harapan bahwa realitas tertinggi bukan kekuasaan atau kekayaan atau kesenangan, melainkan kasih. Harapan bahwa perbedaan tidak perlu mengarah pada konflik, tapi bisa menjadi sumber kekayaan dalam persekutuan. Harapan bahwa kita tidak sendirian, melainkan diciptakan untuk persekutuan dengan Allah dan sesama. Harapan bahwa penderitaan dan kematian bukan kata terakhir, karena Allah di dalam Kristus sudah memasuki penderitaan dan mengalahkan kematian.
Ketika kita merenungkan warisan Tertulianus hampir dua ribu tahun setelah ia hidup, kita menyadari bahwa pergumulannya bukan hanya pergumulan zamannya, tapi juga pergumulan kita. Bagaimana kita bisa memahami Allah dengan cara yang benar dan sesuai kesaksian Alkitab tapi juga bisa diutarakan dengan jelas dalam konteks budaya kita? Bagaimana kita bisa menjaga kesatuan gereja sambil menghormati keragaman? Bagaimana kita bisa hidup sebagai komunitas kasih dalam dunia yang sering dipenuhi kebencian dan perpecahan? Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita di tengah tantangan intelektual dan budaya yang terus berubah?
Tertulianus tidak memberikan jawaban akhir untuk semua pertanyaan ini. Rumusan teologisnya sendiri perlu penyempurnaan oleh generasi-generasi berikutnya. Tapi ia memberikan sesuatu yang sama pentingnya, yaitu komitmen untuk bergumul dengan kebenaran secara serius, keberanian untuk mengembangkan bahasa baru ketika bahasa lama tidak memadai, dan keteguhan untuk mempertahankan kebenaran inti iman meski menghadapi tekanan untuk menyederhanakan atau mengkompromikan.
Dalam semangat ini, kita dipanggil untuk menjadi pewaris Tertulianus di zaman kita saat ini. Bukan dengan sekadar mengulang rumusan-rumusan lama (meskipun itu penting), tapi dengan bergumul secara kreatif tentang bagaimana kebenaran-kebenaran kekal ini bisa diutarakan dan dihidupi dalam konteks kita yang terus berubah. Ajaran Trinitas bukan museum “artefak teologis” yang harus kita kagumi dari kejauhan, melainkan kebenaran hidup yang harus terus-menerus kita pahami kembali, hayati kembali, dan bagikan kembali dengan setiap generasi baru.
Melalui misteri Trinitas mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang melampaui kemampuan kita untuk sepenuhnya memahami. Kita bisa merumuskan, mengutarakan, dan mengajarkan tapi pada akhirnya, kita berdiri di hadapan misteri yang tak terbatas. Allah tidak bisa “dikendalikan” oleh rumusan-rumusan kita, betapa pun tepatnya. Tertulianus memahami ini. Rumusannya adalah upaya manusiawi untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang Allah, tapi ia tidak pernah mengklaim sudah sepenuhnya memahami atau menjelaskan Allah.
Sikap kerendahan hati ini akan memampukan kita menegaskan kebenaran sambil mengakui keterbatasan kita. Di era kita yang sering ditandai baik oleh fundamentalisme yang kaku di satu sisi maupun relativisme yang longgar di sisi lain, Tertulianus menunjukkan jalan tengah, yaitu komitmen pada kebenaran yang dikombinasikan dengan kerendahan hati epistemologis, ketepatan teologis yang dikombinasikan dengan kesadaran akan misteri.
Ajaran Trinitas, sebagaimana dirumuskan pertama kali oleh Tertulianus dan kemudian disempurnakan oleh generasi-generasi teolog setelahnya, tetap menjadi inti iman Kristen. Itu bukan tambahan opsional pada iman Kristen, bukan spekulasi filosofis yang bisa kita abaikan kalau terlalu rumit. Sebaliknya, itu adalah jantung dari segala sesuatu yang kita percayai tentang Allah, tentang diri kita sendiri, dan tentang tujuan keberadaan kita.
Tertulianus, ahli hukum dari Kartago yang telah mengabdikan kehidupan intelektualnya untuk mempertahankan dan menjelaskan kebenaran ini, pantas dikenang bukan hanya sebagai figur sejarah, tapi sebagai bapa rohani yang warisannya terus membentuk dan memperkaya iman kita selaku gereja hingga hari ini.
Ketika kita mengucapkan Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel dalam ibadah, ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ketika kita berdoa kepada Bapa melalui Anak dalam Roh, kita berdiri di atas fondasi yang telah diletakkan Tertulianus hampir dua ribu tahun lalu. Rumusannya “una substantia, tres personae” bergema melalui abad-abad, mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah persekutuan kasih kekal, dan kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi itu dalam waktu dan keabadian.
Ajaran Trinitas mengajarkan kita bahwa di pusat realitas bukan ada kesendirian, melainkan persekutuan; bukan ada dominasi, melainkan kasih yang saling memberi; bukan ada keseragaman, melainkan keragaman dalam kesatuan. Ini adalah visi yang tidak hanya mengubah cara kita berpikir tentang Allah, tapi juga mengubah cara kita hidup di dunia. Ini adalah visi yang mengundang kita untuk memasuki “tarian ilahi” yang sudah berlangsung sejak kekal, untuk menjadi bagian dari cerita kasih yang tidak pernah berakhir.
Warisan utama Tertulianus bukan hanya bahwa ia memberi kita kata-kata untuk mengutarakan misteri, tapi bahwa ia mengundang kita untuk memasuki misteri itu sendiri, untuk hidup dalam cahaya Trinitas, untuk menjadi cerminan dari kasih ilahi dalam dunia yang sangat membutuhkan kasih itu. Dalam perjalanan iman kita, kita terus belajar apa artinya menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah Trinitas untuk hidup dalam relasi, untuk mengasihi dengan kasih yang memberi diri, untuk menemukan identitas kita bukan dalam isolasi tapi dalam persekutuan, untuk menjadi agen rekonsiliasi dalam dunia yang terpecah-pecah.
Melalui warisan Tertulianus kita diingatkan bahwa teologi sejati tidak pernah hanya tentang konsep dan rumusan, tapi tentang kehidupan, yaitu kehidupan yang ditransformasi oleh perjumpaan dengan Allah yang hidup, Allah yang adalah Trinitas yang kudus. Dan dalam perjumpaan itu, kita menemukan bukan hanya kebenaran tentang Allah, tapi juga kebenaran tentang diri kita sendiri dan tentang dunia yang Allah ciptakan dan tebus dengan kasih-Nya.
Pdt. Yohanes Bambang Mulyono
 Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi
Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi