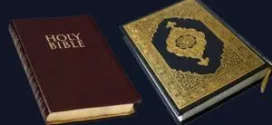Pertanyaan tentang apakah gereja harus menyebut Maria sebagai Theotokos (Bunda Allah), atau Christotokos (Bunda Kristus) bukanlah sekadar perkara istilah, bukan pula persoalan devosi yang bisa dinegosiasikan. Di balik perbedaan ini tersembunyi persoalan kristologis yang menyentuh inti pengakuan iman gereja tentang siapakah Yesus Kristus. Sejarah gereja mencatat bahwa ketika Nestorius, Patriark Konstantinopel, mencoba mengganti gelar Theotokos dengan Christotokos. Akibatnya gereja diguncang oleh pergolakan besar. Konsili Efesus tahun 431 pada akhirnya menyatakan bahwa gereja harus tetap memegang gelar Theotokos bukan dalam rangka untuk meninggikan Maria, melainkan untuk menjaga tegaknya pengajaran tentang inkarnasi Sang Firman.
Dalam suasana gereja Reformasi masa kini, kita melihat kecenderungan untuk menjauh dari istilah Theotokos. Ada yang merasa istilah itu terlalu dekat dengan Katolik, ada yang khawatir akan membuka pintu bagi devosi yang tidak semestinya, ada pula yang menganggap istilah itu tidak cukup alkitabiah. Namun pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apakah keberatan-keberatan ini cukup kuat untuk menyingkirkan suatu rumusan iman yang telah menjadi warisan gereja sedari awal, bahkan diterima para Reformator sendiri? Dan bila suatu gereja memilih untuk berpegang hanya pada Christotokos, apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan?
Kata Theotokos berasal dari Theos (Allah) dan tikto (melahirkan), sehingga berarti “yang melahirkan Allah.” Tentu saja gereja tidak pernah mengajarkan bahwa Maria adalah asal-usul keilahian. Bukan itu maknanya. Theotokos adalah pernyataan tentang Pribadi yang dilahirkan Maria adalah Yesus Kristus, satu Pribadi yang memiliki dua natur, yaitu pribadi dengan kodrat ilahi dan manusiawi. Karena Pribadi itu adalah Allah Putra sendiri, maka Maria disebut Bunda Allah dalam pengertian bahwa ia melahirkan Sang Firman yang menjadi manusia.
Sebaliknya, gelar Christotokos berarti “yang melahirkan Kristus.” Nestorius mengusulkannya untuk menjaga transendensi Allah. Ia bertanya: “Bagaimana mungkin Allah yang kekal dapat dilahirkan?” Pertanyaan itu terdengar wajar. Namun justru dalam usaha melindungi transendensi Allah, Nestorius telah mengorbankan kesatuan Pribadi Kristus. Ia akhirnya membayangkan adanya dua subjek dalam diri Kristus, yaitu subjek Yesus manusia dan subjek Logos ilahi. Kedua subjek tersebut hanya bersatu secara moral, bukan secara hipostatik. Dalam konteks ini gereja berkata “tidak.” Gereja menolak pemahaman Kristus yang terbelah menjadi 2 Subjek.
Sekalipun kata Theotokos tidak muncul secara eksplisit di dalam Perjanjian Lama, esensinya hadir dengan kuat dalam Perjanjian Baru. Elisabet, dipenuhi Roh Kudus, dengan gentar berkata kepada Maria, “Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?” (Luk. 1:43). Kata Kyrios yang dipakainya bukanlah sekadar gelar sopan santun. Sebaliknya kata “Kyrios” sebagai gelar yang dalam teologi Lukas merujuk kepada Tuhan yang menyatakan diri dalam sejarah. Elisabet tidak sedang memberikan pujian manusiawi, melainkan sedang mengakui dengan iman bahwa Anak dalam kandungan Maria adalah Tuhan itu sendiri.
Yohanes 1:14 menegaskan dengan sangat jelas bahwa “Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.” Ketika Alkitab menyatakan bahwa Firman menjadi manusia, yang dimaksud bukanlah “natur ilahi” yang turun ke dunia sebagai suatu entitas abstrak, melainkan Pribadi Firman itu sendiri, yaitu Sang Logos yang sejak kekal adalah Allah. Maria tidak melahirkan sebuah natur, dan bukan pula melahirkan sekadar kemanusiaan Yesus. Ia melahirkan Pribadi Sang Firman yang mengambil natur manusia di dalam rahimnya.
Rasul Paulus menggemakan kebenaran ini ketika menulis, “Dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan” (Kol. 2:9). Kristus yang lahir ke dalam sejarah manusia itu bukan fragmen keilahian, bukan manifestasi parsial, tetapi kepenuhan Allah yang hadir secara jasmaniah. Bahkan surat Roma 9:5 menyebut Kristus sebagai “Allah yang di atas segala sesuatu, yang harus dipuji sampai selama-lamanya.” Dengan demikian, Alkitab tidak memberikan ruang bagi pengertian bahwa Maria melahirkan manusia semata. Sebaliknya Maria melahirkan Allah Putra yang menjadi manusia. Maka gelar Theotokos bukanlah elevasi (peninggian) diri Maria, melainkan konsekuensi logis dari pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah satu Pribadi yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia.
Konsili Efesus (431) menegaskan hal ini dengan bahasa yang amat tegas. Dalam anatema pertamanya, konsili Efesus menyatakan bahwa siapa pun yang tidak mengakui Maria sebagai Theotokos (karena ia melahirkan Firman Allah yang menjadi daging) biarlah ia terkutuk. Anatema dalam konsili Efesus tersebut bukanlah ekspresi “ultradevosi” kepada Maria, melainkan upaya gereja menjaga terhadap kemurnian kristologi. Gereja memahami bahwa jika gelar Theotokos dicabut, maka keseluruhan struktur pengakuan tentang inkarnasi akan runtuh. Yang dipertaruhkan bukan pemuliaan diri Maria, melainkan Kristus sendiri. Karena itu konsili Efesus menetapkan bahwa Maria disebut Bunda Allah (Theotokos) justru untuk melindungi pernyataan iman bahwa Yesus yang ia lahirkan adalah Pribadi ilahi yang benar-benar menjadi manusia.
Dua puluh tahun kemudian, Konsili Khalsedon (451) memantapkan pondasi ini melalui rumusan kristologis yang kelak menjadi tonggak ortodoksi gereja, yaitu “Kristus adalah satu Pribadi, satu Hipostasis, dengan dua natur ilahi dan manusia yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah.” Dalam kesatuan hipostatik ini, gereja mengakui bahwa Pribadi yang lahir dari Maria bukanlah subjek manusiawi yang terpisah dari Sang Firman, tetapi Pribadi Allah Putra sendiri. Dengan demikian gelar Theotokos menjadi konsekuensi langsung dari unio hypostatica. Bila Kristus adalah satu Pribadi, maka Maria melahirkan Pribadi itu. Dan Pribadi itu adalah Allah.
Bagaimana dengan para Reformator? Banyak orang berasumsi bahwa gereja-gereja Reformasi meninggalkan istilah Theotokos karena hendak menjauh dari warisan Katolik. Namun gambaran itu tidak sesuai fakta sejarah. Martin Luther dengan sangat terbuka mempertahankan Theotoko. Dalam khotbahnya tentang Yohanes 1:14, Luther berkata, “Maria adalah Bunda Allah sejati, karena Pribadi yang ia lahirkan adalah Allah.” Baginya, siapa yang menolak Theotokos sesungguhnya sedang merusak pengakuan tentang keilahian Kristus. Luther kembali menegaskan hal ini dalam tafsir Magnificat dengan menyebut diri Maria sebagai Gottesgebärerin (“Dia yang melahirkan Allah”, atau “Bunda Allah”), bukan karena ia melahirkan keilahian, melainkan karena ia melahirkan Pribadi yang adalah Allah.
John Calvin, meskipun lebih waspada terhadap devosi yang berlebihan, tetap menerima istilah ini. Dalam Institutes, ia menafsirkan sapaan Elisabet, “Ibu Tuhanku,” sebagai pengakuan bahwa apa yang dapat dikatakan tentang natur manusia Kristus dapat juga dipredikasikan kepada Pribadi ilahi-Nya—karena kedua natur itu bersatu dalam satu Pribadi. Calvin menegaskan doktrin communicatio idiomatum, yang membuat pengakuan Theotokos bukan hanya wajar tetapi perlu.
Huldrych Zwingli pun berdiri pada posisi yang sama. Dalam Fidei Expositio, ia menyatakan bahwa “Maria adalah Bunda Allah sejati, karena Kristus yang dilahirkannya adalah Allah sejati dan manusia sejati dalam satu Pribadi.” Ketiga Reformator utama, yaitu Luther, Calvin, dan Zwingli berjalan seiring dengan tradisi gereja mula-mula dalam mengafirmasi Theotokos, bukan untuk meninggikan Maria di atas tempat yang semestinya, melainkan untuk menjaga agar Kristus tidak dipahami secara keliru.
Dengan demikian, ketika sebuah gereja masa kini memilih untuk memakai Christotokos dan menolak Theotokos, ia tidak sedang membuat keputusan semantik yang netral. Ia sedang melakukan perubahan yang membawa lima konsekuensi teologis yang serius.
Pertama, ketika gereja memilih meninggalkan istilah Theotokos dan menggantinya dengan Christotokos, sesungguhnya ada bahaya besar yang mengintai, yaitu kembali menghidupkan ajaran Nestorianisme. Ajaran Nestorius telah dikutuk dalam Konsili Efesus sebab memecah Kristus menjadi dua pribadi, yaitu seorang manusia Yesus di satu pihak, dan Logos ilahi di pihak lain. Ketika gereja berkata bahwa Maria “hanya” melahirkan Kristus sebagai manusia, maka kita tanpa sadar sedang mengatakan bahwa yang dilahirkan dari rahim Maria hanyalah natur kemanusiaan, sedangkan Sang Logos berada pada level terpisah. John McGuckin mengingatkan bahwa menolak Theotokos pada akhirnya akan mengecilkan misteri inkarnasi menjadi sekadar pendiaman Allah dalam seorang manusia sehingga bukan lagi penyatuan hipostatik antara Allah Putra dan natur manusia. Pemikiran atau ajaran ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kembali ke jurang bidat lama yang pernah menggoncang gereja. Sebab inkarnasi bukan peristiwa “Allah masuk ke dalam seorang manusia,” tetapi Allah Putra yang berkenan mengambil natur manusia ke dalam kesatuan Pribadi-Nya.
Kedua, penolakan terhadap Theotokos pasti mengaburkan doktrin inkarnasi. Doktrin inkarnasi mengatakan bahwa Pribadi Putra, bukan sekadar natur ilahi, menjadi manusia. Maria tidak melahirkan “natur manusia” seperti orang melahirkan sebuah kualitas. Ia melahirkan Pribadi yang memiliki natur. Thomas Aquinas mengungkapkannya dengan sangat jernih bahwa Maria melahirkan Pribadi, bukan natur; dan karena Pribadi itu adalah Allah, maka Maria layak disebut Bunda Allah. Jika gereja membatasi diri hanya pada istilah Christotokos, maka inkarnasi akan tereduksi menjadi peristiwa yang menyentuh aspek manusia Yesus saja, sementara keilahian-Nya tetap berada di luar peristiwa kelahiran itu. Padahal, inti inkarnasi adalah bahwa Pribadi Putra benar-benar masuk ke dalam sejarah manusia melalui kelahiran dari Maria.
Ketiga, pemutusan hubungan dari Theotokos akan melemahkan kesaksian gereja tentang kesatuan Pribadi Kristus. Rumusan Khalsedon menegaskan bahwa Kristus adalah satu Pribadi dengan dua natur. Segala yang Ia lakukan baik sebagai Allah maupun sebagai manusia dilakukan oleh satu Subjek yang sama. Karena itu, kematian Kristus di salib memiliki nilai kekal bahwa yang menderita itu bukan sekadar manusia Yesus, melainkan Pribadi Allah Putra yang telah mengambil rupa manusia. Louis Bouyer memperingatkan bahwa jika Maria bukan Bunda Allah, maka Kristus yang tersalib bukan Allah. Konsekuensinya adalah bila demikian, maka salib kehilangan nilai penebusan yang tidak terbatas. Kesalahan kecil dalam istilah akan berujung pada keruntuhan besar dalam soteriologi. Sebab bila yang wafat di kayu salib hanyalah manusia, maka penebusan menjadi mustahil.
Keempat, penolakan terhadap Theotokos sering kali tidak berdasar dari Alkitab, melainkan dari kekuatiran devosional. Prinsip sola Scriptura tidak pernah menolak istilah Theotokos, karena Alkitab sendiri menyebut Maria sebagai “ibu Tuhanku” (Luk. 1:43), dan Yohanes 1:14 menegaskan bahwa Firman menjadi manusia. Tidak ada ayat yang memerintahkan gereja untuk mengganti Theotokos dengan Christotokos. Sering kali, keberatan-keberatan yang muncul berasal dari alasan “ekstra-teologis” yaitu keinginan menjaga jarak dari Gereja Katolik atau kekuatiran akan “Mariologi” berlebihan. Namun respons dan solusi yang benar bukan menghapus istilahnya, melainkan mengajarkan maknanya secara tepat dalam terang Alkitab.
Kelima, penggunaan eksklusif Christotokos akan melemahkan apologetika terhadap Unitarianisme dan Islam. Kedua tradisi ini kerap menyerang iman Kristen dengan logika sederhana, yaitu “Allah tidak dilahirkan. Yesus dilahirkan. Maka Yesus bukan Allah.” Pengakuan Theotokos sebenarnya memberikan jawaban yang kuat dan presisi bahwa yang dilahirkan adalah Pribadi ilahi yang mengambil natur manusia, bukan keilahian Allah yang abai sifat kekalnya. Dalam natur ilahi-Nya, Kristus tidak lahir; dalam natur manusia-Nya, Ia dilahirkan. Pengakuan ganda ini hanya mungkin jika kesatuan Pribadi Kristus dipertahankan. Jika gereja menolak Theotokos, maka kita membiarkan argumen Unitarian dan Islam berjalan tanpa sanggahan kristologis yang kokoh.
Memang kenyataan sering menunjukkan bahwa sebagian gereja Injili atau Reformed modern memilih untuk menghindari istilah Theotokos. Alasannya beragam, misalnya kekuatiran mariologi, preferensi bahasa, hingga ketegangan dengan umat Muslim. Namun semua keberatan ini dapat dijawab lewat katekesasi yang baik. R. C. Sproul mengingatkan bahwa penyalahgunaan devosi tidak boleh membuat kita mengesampingkan pengakuan kristologis yang benar. Gelar Maria sebagai Theotokos berkaitan dengan pernyataan tentang Kristus, bukan tentang diri Maria. Tugas gereja adalah mengajar dengan benar, bukan menghindar dari istilah yang memiliki bobot teologis yang tak tergantikan.
Karena itu, mengikuti teladan Luther, Calvin, dan Zwingli, gereja Protestan seharusnya tidak perlu takut menerima Theotokos sambil tetap menjaga batas devosi Maria dalam koridor Alkitab. Ketiga tokoh reformator memakai istilah itu bukan karena mereka mengagumi Maria secara berlebihan, melainkan karena mereka ingin menjaga agar Kristus tidak dipahami secara keliru.
Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan tentang Maria, tetapi tentang siapa diri Yesus Kristus itu. Apakah Kristus adalah Allah sejati yang menjadi manusia? Atau Ia hanya seorang manusia yang diilhami Allah? Gereja mula-mula telah memberikan jawabannya. Para Reformator telah mengafirmasinya. Melalui gelar Maria sebagai Theotokos merupakan media pengakuan bahwa Pribadi yang lahir dari Maria adalah Allah Putra sendiri yang mengenakan natur manusia. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu, Maria adalah Bunda Allah, bukan dalam pengertian karena ia melahirkan keilahian, melainkan karena ia melahirkan Pribadi ilahi yang masuk ke dalam sejarah manusia.
BIBLIOGRAFI
Calvin, John. Institutes of the Christian Religion. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. 2 vols. Library of Christian Classics. Philadelphia: Westminster Press, 1960.
Cyril of Alexandria. Five Tomes Against Nestorius. In Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 14, edited by Philip Schaff and Henry Wace. Grand Rapids: Eerdmans, 1956.
Luther, Martin. Luther’s Works. American Edition. 55 vols. Edited by Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann. St. Louis: Concordia; Philadelphia: Fortress, 1955–1986.
Zwingli, Huldrych. Fidei Expositio (1531). In On Providence and Other Essays, edited by William John Hinke. Durham: Labyrinth Press, 1983.
Dokumen Konsili
Council of Ephesus (431). Canons and decrees. In The Seven Ecumenical Councils, edited by Henry R. Percival. Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Vol. 14. Grand Rapids: Eerdmans, 1956.
Council of Chalcedon (451). The Definition of Chalcedon. In Creeds of the Churches, edited by John H. Leith, 3rd ed. Louisville: Westminster John Knox, 1982.
Sumber Sekunder
Aquinas, Thomas. Summa Theologiae. Translated by Fathers of the English Dominican Province. 5 vols. New York: Benziger Brothers, 1948. III, q. 35, a. 4.
Bouyer, Louis. The Eternal Son: A Theology of the Word of God and Christology. Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 1978.
González, Justo L. A History of Christian Thought, Vol. 1: From the Beginnings to the Council of Chalcedon. Revised edition. Nashville: Abingdon Press, 1987.
Kelly, J. N. D. Early Christian Doctrines. 5th edition. London: Continuum, 1977.
McGrath, Alister E. Reformation Thought: An Introduction. 4th edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.
McGuckin, John Anthony. Saint Cyril of Alexandria and the Christological Controversy. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2004.
Pelikan, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, Vol. 1: The Emergence of the Catholic Tradition (100–600). Chicago: University of Chicago Press, 1971.
Sproul, R. C. Essential Truths of the Christian Faith. Wheaton: Tyndale House, 1992.
Torrance, Thomas F. The Trinitarian Faith: The Evangelical Theology of the Ancient Catholic Church. Edinburgh: T&T Clark, 1988.
Ware, Kallistos. The Orthodox Way. Revised edition. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1995.
Weinandy, Thomas G. Does God Suffer? Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2000.
Artikel Jurnal
Cross, Richard. “Nestorianism and the Communicatio Idiomatum.” Scottish Journal of Theology 63, no. 2 (2010): 127–140.
Fairbairn, Donald. “Patristic Soteriology: Three Trajectories.” Journal of the Evangelical Theological Society 50, no. 2 (2007): 289–310.
Keating, Daniel A. “The Practical Importance of the Christology of Cyril of Alexandria.” Pro Ecclesia 8, no. 4 (1999): 404–416.
Pdt. Em. Yohanes Bambang Mulyono
 Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi
Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi