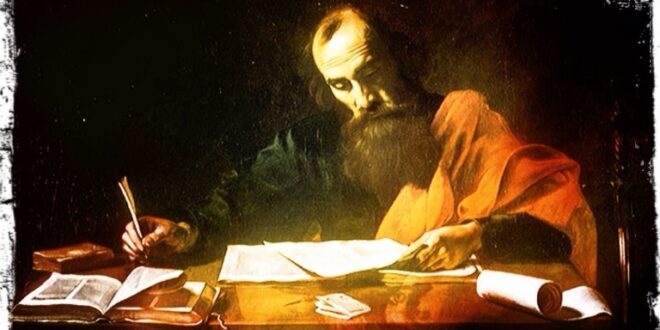Roma 3:1–20 merupakan salah satu teks teologis yang paling mendasar sekaligus paling diperdebatkan dalam tradisi Kristen. Dalam perikop ini, rasul Paulus merumuskan secara tajam argumentasi tentang kondisi universal manusia di hadapan Allah, peran hukum Taurat, serta kebutuhan mutlak akan penyelamatan ilahi. Hampir setiap klaim teologis yang dikemukakan rasul Paulus dalam bagian ini, bagaimanapun, berhadapan dengan penolakan mendasar dari perspektif Islam. Perbedaan tersebut tidak sekadar menyangkut tafsir atas teks, melainkan mencerminkan dua paradigma teologis yang secara fundamental berbeda dalam memahami hakikat Allah, manusia, dosa, dan jalan keselamatan.
Surat Roma ditulis rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi dalam konteks ketegangan teologis di gereja mula-mula. Pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul, yaitu apakah keistimewaan Israel masih memiliki makna? Apakah hukum Taurat tetap mengikat umat Allah? Bagaimana relasi antara iman kepada Kristus dan ketaatan terhadap Taurat? Dalam alur argumentasi yang panjang, Roma 3:1–20 berfungsi sebagai titik kulminasi yang dimulai sejak Roma 1:18, ketika rasul Paulus menegaskan bahwa seluruh umat manusia baik Yahudi maupun non-Yahudi berada dalam kondisi yang sama, yaitu di bawah kuasa dosa dan karena itu sama-sama membutuhkan penyelamatan dari Allah.
Teks ini dibuka dengan sebuah pertanyaan retoris, “Jadi, apakah kelebihan orang Yahudi? Atau apakah gunanya sunat?” Rasul Paulus menjawabnya secara tegas, “Banyak sekali, terutama karena kepada merekalah dipercayakan firman Allah.” Jawaban ini mengakui keistimewaan historis Israel sebagai penerima wahyu ilahi yang pertama. Namun, keistimewaan tersebut tidak berarti superioritas moral atau jaminan keselamatan secara otomatis.
Rasul Paulus kemudian mengangkat sebuah pertanyaan yang bersifat teologis sekaligus filosofis, bagaimana jika sebagian orang Israel tidak setia? Apakah ketidakpercayaan mereka membatalkan kesetiaan Allah? Dengan penegasan yang kuat ia menjawab, “Sekali-kali tidak!” seraya mengutip Mazmur 51:4 yaitu “Allah tetap benar meskipun semua manusia adalah pembohong.” Melalui pernyataan ini, rasul Paulus menegaskan sebuah prinsip teologis yang fundamental tentang kesetiaan dan kebenaran Allah yang tidak pernah bergantung pada respons manusia.
Argumentasi ini selanjutnya memunculkan dilema etis yang dibahas rasul Paulus dalam ayat 5–8. Jika ketidakadilan manusia justru menonjolkan keadilan Allah, bukankah tidak adil jika Allah tetap menghukum manusia? Rasul Paulus menolak logika ini secara tegas. Jika penalaran semacam itu diterima, maka seluruh dasar penghakiman ilahi akan runtuh. Dalam konteks ini, rasul Paulus juga menanggapi fitnah yang dialamatkan kepadanya, seolah-olah ajarannya mendorong prinsip “berbuat jahat supaya yang baik terjadi.” Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai penyimpangan serius terhadap ajaran kasih karunia yang justru akan ia uraikan secara lebih mendalam dalam bagian-bagian selanjutnya.
Klimaks argumentasi rasul Paulus tercapai dalam ayat 9–20 melalui sebuah deklarasi yang bersifat mengejutkan sekaligus menentukan, “Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka semua berada di bawah kuasa dosa.” Pernyataan ini menghadirkan sebuah tesis yang radikal, yakni bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat dan orang non-Yahudi yang tidak memilikinya dalam hal status moral di hadapan Allah. Kepemilikan Taurat tidak menghasilkan keunggulan moral yang menentukan. Sebaliknya, seluruh umat manusia ditempatkan pada posisi yang sama di bawah penghakiman ilahi.
Untuk menopang tesis tersebut, rasul Paulus menggunakan teknik rabinik yang dikenal sebagai catena, yakni rangkaian kutipan dari Mazmur dan Yesaya. Kutipan-kutipan ini melukiskan kerusakan manusia secara menyeluruh, yaitu “Tidak ada yang benar, seorang pun tidak; tidak ada seorang pun yang mencari Allah; kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga; lidah mereka penuh tipu daya; bibir mereka mengandung bisa ular; kaki mereka cepat menumpahkan darah; rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu.” Dengan cara ini, rasul Paulus menunjukkan bahwa kesaksian Kitab Suci sendiri bersifat konsisten dalam menilai kondisi manusia.
Penting dicatat bahwa rasul Paulus tidak sedang menyatakan bahwa setiap manusia melakukan setiap bentuk kejahatan pada setiap waktu. Yang ia gambarkan adalah kondisi umum umat manusia yang telah jatuh, yaitu adanya kapasitas universal untuk kejahatan serta ketiadaan kebenaran sejati ketika manusia diukur berdasarkan standar kekudusan Allah. Pemahaman inilah yang dalam perkembangan selanjutnya dirumuskan sebagai doktrin total depravity dalam teologi Reformed, yakni bahwa seluruh aspek eksistensi manusia yaitu seluruh akal budi, kehendak, emosi, dan tindakan telah terpengaruh oleh dosa dan karena itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri di hadapan Allah.
Ayat 19–20 menghadirkan kesimpulan yang bersifat final sekaligus menempelak, “Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.” Di titik ini, rasul Paulus melakukan sebuah manuver teologis yang cermat dan strategis. Dengan menggunakan Kitab Suci Perjanjian Lama, ia menunjukkan bahwa bahkan Israel yaitu umat yang menerima hukum Taurat tidak dapat memperoleh pembenaran melalui hukum tersebut. Taurat tidak berfungsi sebagai sarana keselamatan, melainkan sebagai alat pewahyuan dosa, yang memberikan pengenalan akan dosa. Hukum, dalam kerangka ini, bekerja seperti sebuah cermin. Taurat menyingkapkan kekotoran, tetapi tidak memiliki kuasa untuk membersihkannya.
Dengan demikian, seluruh kemungkinan pembenaran diri manusia telah ditutup, “supaya tersumbat setiap mulut” dan seluruh dunia menjadi bersalah di hadapan Allah. Kesimpulan ini tidak berdiri sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai persiapan teologis bagi solusi yang akan rasul Paulus paparkan selanjutnya, yakni kebenaran Allah yang dianugerahkan melalui iman kepada Yesus Kristus.
Namun, hampir setiap unsur argumentasi ini ditolak dalam kerangka teologi Islam, dimulai dari persoalan otoritas rasul Paulus sendiri. Al-Qur’an tidak pernah mengakui jabatan rasul dari Paulus, dan dalam pandangan mayoritas ulama Muslim, rasul Paulus dipahami sebagai figur yang bertanggung jawab atas pergeseran Kekristenan dari monoteisme murni yang diyakini telah diajarkan oleh Yesus. Sejumlah sarjana bahkan menilainya sebagai muharif, yakni pihak yang mengubah atau menyimpangkan ajaran asli. Oleh karena itu, sejak titik awalnya, otoritas teologis rasul Paulus sudah dipersoalkan secara mendasar dalam perspektif Islam, sehingga keseluruhan bangunan argumentasi Roma 3:1–20 sulit diterima dalam kerangka teologis Islam.
Pada tingkat yang lebih fundamental, Islam menolak premis dasar Roma 3:1–20, yakni pandangan tentang kondisi manusia yang secara universal telah rusak oleh dosa. Dalam antropologi Islam, manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berdosa. Setiap manusia lahir dalam kondisi fitrah, yaitu suatu keadaan asli yang suci, bersih, dan secara alamiah cenderung kepada monoteisme serta kebaikan. Sebuah hadis yang sering dikutip menyatakan, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah; maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” Dengan demikian, Islam secara tegas menolak doktrin dosa asal.
Penolakan ini berakar kuat dalam narasi Al-Qur’an tentang Adam dan Hawa. Ketika keduanya melanggar larangan Allah, tindakan tersebut dipahami sebagai dosa personal, bukan dosa yang diwariskan. Al-Qur’an menegaskan bahwa setelah pertobatan Adam, Allah mengampuninya, “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya” (QS. Al-Baqarah 2:37). Tidak terdapat konsep transmisi dosa kepada seluruh keturunan manusia. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit, yaitu “Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (QS. Al-An‘am 6:164).
Dalam kerangka ini, gambaran rasul Paulus tentang manusia bahwa “tidak ada yang benar, seorang pun tidak; tidak ada seorang pun yang mencari Allah; kerongkongan seperti kubur yang ternganga” dipandang dalam ajaran Islam sebagai bentuk pesimisme antropologis yang berlebihan dan tidak selaras dengan keadilan Allah terhadap ciptaan-Nya. Islam memang mengakui bahwa manusia memiliki kapasitas untuk berbuat dosa, tetapi pada saat yang sama menegaskan adanya kapasitas untuk kebaikan dan ketaatan. Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk yang diberi potensi ganda, “Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya” (QS. Asy-Syams 91:7–8). Manusia, dengan kehendak bebasnya, dipanggil untuk memilih di antara kedua kemungkinan tersebut.
Oleh karena itu, klaim rasul Paulus bahwa “tidak ada yang benar, seorang pun tidak” dipandang problematis dalam perspektif Islam karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi. Jika manusia benar-benar tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kebenaran sejati, maka dasar bagi penghakiman ilahi menjadi sulit dipertahankan. Islam menegaskan sebaliknya, yaitu Allah menghakimi secara adil dan menghargai setiap perbuatan baik, sekecil apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an, “Allah tidak berbuat zalim seberat zarrah pun; dan jika ada kebajikan sekecil apa pun, Allah akan melipatgandakannya” (QS. An-Nisa 4:40).
Penolakan Islam terhadap Roma 3:1–20 juga berakar pada perbedaan yang mendasar dalam memahami fungsi hukum ilahi. Pernyataan rasul Paulus bahwa “tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa” dipandang sebagai proposisi yang sangat problematis dalam kerangka teologi Islam. Dalam pemahaman Islam, hukum Syariah bukanlah beban atau jebakan yang menyingkapkan ketidakmampuan manusia, melainkan rahmat Allah, petunjuk yang jelas, dan jalan menuju kehidupan yang benar serta keselamatan. Al-Qur’an menggambarkan Taurat secara positif, “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat; di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya” (QS. Al-Ma’idah 5:44). Jika hukum Taurat mengandung petunjuk dan cahaya, maka sulit diterima bahwa fungsinya semata-mata adalah untuk menyatakan kegagalan manusia di hadapan Allah. Dalam perspektif Islam, hukum ilahi diturunkan bukan untuk mengekspos kelemahan manusia, melainkan untuk membimbingnya menuju ketaatan dan kehidupan yang benar. Karena itu, ketaatan kepada Syariah dipahami sebagai jalan keselamatan, bukan sebagai penghalang bagi keselamatan.
Perbedaan ini bermuara pada pertentangan soteriologis yang paling fundamental, yakni mengenai relasi antara iman, perbuatan, dan keselamatan. Roma 3:20 dan 3:28 menjadi landasan utama doktrin pembenaran oleh iman saja (sola fide) dalam tradisi Kristen. Islam menolak dikotomi ini secara prinsipil. Iman dan amal tidak dapat dipisahkan atau dipertentangkan satu sama lain. Al-Qur’an secara konsisten menggunakan formula “orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan” untuk menggambarkan mereka yang memperoleh keselamatan. Surah Al-‘Asr merumuskan prinsip ini secara ringkas dan padat, “Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.” Dalam kerangka ini, keselamatan menuntut kesatuan antara iman dan tindakan; tidak terdapat indikasi bahwa iman semata, tanpa perbuatan, sudah mencukupi untuk memperoleh keselamatan.
Teologi rasul Paulus tentang kasih karunia yang tidak bersyarat kerap dipandang, dari perspektif Islam, membuka jalan menuju antinomianisme, yakni pandangan bahwa hukum moral tidak lagi memiliki relevansi normatif. Meskipun rasul Paulus sendiri secara eksplisit menolak tuduhan ini, para kritikus Muslim berargumen bahwa antinomianisme merupakan konsekuensi logis yang sulit dihindari. Jika seseorang dibenarkan semata-mata oleh iman tanpa keterkaitan esensial dengan perbuatan, maka dasar motivasi bagi ketaatan moral dipertanyakan. Islam, sebaliknya, menegaskan bahwa kasih karunia Allah memang nyata, luas, dan melimpah, tetapi selalu beroperasi dalam kerangka keadilan ilahi. Allah menerima pertobatan dan melipatgandakan pahala, namun hal itu tidak meniadakan tanggung jawab moral manusia di hadapan-Nya.
Kritik Islam juga diarahkan pada cara rasul Paulus menggunakan Kitab Suci Ibrani. Rangkaian kutipan (catena) dalam Roma 3:10–18 dinilai diambil di luar konteks aslinya. Sebagai contoh, Mazmur 14:1–3 yang menyatakan, “Tidak ada yang berbuat baik,” dalam konteks awalnya merujuk pada kategori tertentu, yakni orang-orang bebal yang menyangkal Allah, bukan pada seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Dengan menggeneralisasikan pernyataan tersebut menjadi penilaian universal tentang kondisi manusia, rasul Paulus dipandang telah melakukan apa yang dalam tradisi Islam disebut sebagai tahrif maknawi, yakni distorsi atau penggeseran makna teks.
Lebih jauh, metode teologis rasul Paulus yang bersifat dialektis ditandai oleh pola pertanyaan dan jawaban, keberatan dan sanggahan dipahami oleh para pengkritik Muslim sebagai indikasi bahwa pemikirannya merupakan hasil refleksi manusiawi, bukan wahyu ilahi secara langsung. Dalam konsepsi Islam tentang wahyu, seorang nabi menerima firman Allah sebagai pesan yang utuh dan final, bukan melalui proses penalaran teologis atau konstruksi argumentatif. Oleh karena itu, cara rasul Paulus membangun teologinya sendiri sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan terhadap klaim otoritas ilahinya dalam perspektif Islam.
Dari perspektif Islam, terdapat kontradiksi mendasar antara ajaran Yesus dan teologi rasul Paulus. Yesus sendiri, dalam Matius 5:17–19, menegaskan dengan sangat jelas, “Jangan kamu sangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat.” Pernyataan ini dipahami dalam Islam sebagai afirmasi tegas atas keberlakuan hukum Taurat yang berkelanjutan.
Rasul Paulus, sebaliknya, menyatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan melalui hukum Taurat dan bahwa kebenaran Allah dinyatakan “terlepas dari hukum Taurat.” Bagi banyak pemikir Muslim, perbedaan ini bukan sekadar nuansa teologis, melainkan sebuah kontradiksi yang jelas. Konsekuensinya, rasul Paulus dipandang telah menyimpang dari ajaran asli Isa al-Masih, yang dalam pemahaman Islam tetap menegaskan kesetiaan pada hukum Allah.
Pertentangan serupa juga tampak dalam pemahaman mengenai keistimewaan Israel dan sejarah keselamatan. Rasul Paulus mengakui bahwa orang Yahudi memiliki kelebihan karena kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Meskipun ia menegaskan bahwa keistimewaan tersebut tidak menjamin keselamatan, struktur teologinya tetap mempertahankan sebuah narasi yang relatif linear, bergerak dari Israel menuju Kristus sebagai titik klimaks sejarah keselamatan. Islam menolak partikularisme semacam ini secara prinsipil.
Meskipun terdapat pertentangan yang bersifat fundamental, beberapa titik temu potensial antara teologi rasul Paulus dan Islam tetap dapat diidentifikasi. Pertama, baik rasul Paulus maupun Islam sama-sama menegaskan kedaulatan Allah yang absolut. Keduanya mengakui bahwa Allah adalah sumber utama kebenaran, hukum, dan keselamatan, serta bahwa inisiatif ilahi memiliki peran yang menentukan dalam relasi antara Allah dan manusia. Kedua, keduanya secara tegas mengkritik kesombongan religius. Ketika rasul Paulus mengajukan pertanyaan, “Adakah kita lebih baik?” lalu menjawabnya, “Sama sekali tidak!”, ia sedang membongkar klaim keunggulan religius yang bertumpu pada identitas etnis atau privilese historis.
Kritik yang sejalan juga ditemukan dalam Al-Qur’an terhadap klaim eksklusivitas Yahudi dan Kristen sebagai “anak-anak Allah” yang istimewa, “Katakanlah, ‘Lalu mengapa Dia menyiksa kamu karena dosa-dosamu?’ Tetapi kamu hanyalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan” (QS. Al-Ma’idah 5:18). Dalam kedua tradisi, kesalehan tidak diukur oleh identitas, melainkan oleh relasi yang benar dengan Allah. Ketiga, baik rasul Paulus maupun Islam sepakat bahwa manusia membutuhkan pertolongan ilahi untuk mencapai tujuan moral dan spiritualnya. Meskipun Paulus menekankan ketergantungan total pada kasih karunia Allah, sementara Islam menegaskan adanya kerja sama antara usaha manusia dan rahmat ilahi, keduanya mengakui bahwa manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan atau keselamatan dengan kekuatannya sendiri semata.
Namun demikian, titik-titik temu ini tidak mampu menutupi perbedaan-perbedaan mendasar yang pada akhirnya sulit untuk dijembatani. Perbedaan antropologis merupakan yang paling krusial. Pandangan rasul Paulus tentang manusia sebagai makhluk yang secara universal berada di bawah kuasa dosa, tidak memiliki kebenaran sejati, dan tidak mampu mencari Allah tanpa terlebih dahulu digerakkan oleh inisiatif kasih karunia-Nya, sangat asing bagi teologi Islam. Dalam perspektif Islam, pandangan semacam ini bukan hanya terlalu pesimistis, tetapi juga dipandang tidak adil terhadap ciptaan Allah, bahkan berpotensi mengimplikasikan bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang cacat sejak awal.
Dari sudut pandang Islam, jika manusia diciptakan dalam keadaan rusak secara total, maka dasar pertanggungjawaban moral menjadi problematis. Bagaimana manusia dapat dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang sejak awal berada di luar kemampuannya? Lebih jauh lagi, pandangan tersebut berpotensi menempatkan Allah sebagai penyebab utama kejahatan, suatu implikasi yang sepenuhnya ditolak dalam teologi Islam. Dengan demikian, perbedaan ini tidak sekadar bersifat doktrinal, melainkan menyentuh jantung pemahaman masing-masing tradisi tentang keadilan Allah dan martabat manusia.
Perbedaan soteriologis antara rasul Paulus dan Islam juga bersifat sangat mendasar. Bagi rasul Paulus, keselamatan adalah pemberian murni Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Hukum tidak memiliki kapasitas untuk menyelamatkan, karena fungsinya terbatas pada kenyataan dosa dan pengungkapan ketidakmampuan manusia di hadapan Allah. Dalam kerangka Islam, konsep ini dipandang problematis dalam beberapa hal. Pertama, ia berpotensi mereduksi fungsi hukum ilahi menjadi tidak efektif, bahkan kontraproduktif. Kedua, ia dianggap melemahkan prinsip tanggung jawab moral manusia. Ketiga, ia menciptakan dikotomi antara iman dan amal yang tidak dikenal dalam struktur teologis Islam, di mana keduanya selalu dipahami sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Perbedaan yang tidak kalah signifikan juga muncul dalam pemahaman tentang wahyu. Dalam teologi Islam, wahyu dipahami sebagai komunikasi langsung dari Allah yang diturunkan dalam bentuk firman yang telah utuh dan final. Sebaliknya, gaya penulisan rasul Paulus dalam Surat Roma yang ditandai oleh argumentasi dialektis, pertanyaan-pertanyaan retoris, serta respons terhadap berbagai keberatan menampakkan proses refleksi dan penalaran manusiawi. Teks Roma tidak diawali dengan formula profetik seperti “Demikianlah firman Tuhan,” melainkan disampaikan dengan otoritas kerasulan Paulus sendiri, yang mengembangkan teologinya melalui pengalaman, interpretasi Kitab Suci, dan penalaran sistematis.
Dari perspektif Islam tentang wahyu, ciri-ciri tersebut dipahami sebagai indikasi bahwa surat Roma bukanlah wahyu ilahi dalam pengertian yang sejati, melainkan hasil konstruksi teologis seorang tokoh religius. Karena itu, perbedaan ini tidak hanya menyangkut isi doktrin, tetapi juga menyentuh persoalan paling mendasar mengenai sumber dan otoritas kebenaran teologis itu sendiri.
Pertanyaan mengenai bagaimana mengevaluasi dua sistem teologis yang begitu berbeda merupakan persoalan filosofis yang mendalam. Masing-masing sistem memiliki logika internal, konsistensi konseptual, dan daya jelaskan (explanatory power) yang khas. Dari dalam kerangka teologi Kristen Pauline, penekanan pada dosa universal dan kasih karunia ilahi menafsirkan pengalaman manusia tentang kegagalan moral yang berulang serta kebutuhan akan transformasi yang tidak dapat dihasilkan oleh usaha manusia semata. Sebaliknya, dari dalam sistem teologi Islam, penekanan pada fitrah dan tanggung jawab moral memberikan penjelasan yang kuat atas pengalaman universal tentang suara hati nurani, kapasitas manusia untuk melakukan kebaikan, dan intuisi moral yang tertanam dalam diri manusia.
Oleh karena itu, dialog antara kedua perspektif ini harus diawali dengan pengakuan yang jujur bahwa yang dipertaruhkan bukanlah sekadar perbedaan terminologi atau penekanan teologis, melainkan perbedaan paradigma yang bersifat fundamental. Muslim dan Kristen tidak menyembah Allah yang sama dalam pengertian memiliki pemahaman yang identik tentang siapa Allah itu dan bagaimana Ia berelasi dengan dunia. Dalam teologi Islam, Allah dipahami sebagai monad absolut yang sepenuhnya transenden, tidak berinkarnasi, tidak memiliki Anak, dan berhubungan dengan dunia terutama melalui wahyu dan hukum ilahi. Sebaliknya, dalam teologi Kristen Pauline, Allah dipahami sebagai Allah Trinitas yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus, yang menebus dunia melalui pengorbanan diri, dan yang menganugerahkan Roh Kudus untuk diam dan bekerja di dalam diri orang percaya. Perbedaan ini menyentuh inti identitas Allah itu sendiri dan dengan demikian membentuk seluruh bangunan antropologi, soteriologi, dan etika dalam masing-masing tradisi.
Apakah dialog yang bermakna mungkin dilakukan antara dua sistem teologis yang sedemikian berbeda? Jika yang dimaksud dengan dialog adalah tercapainya konsensus teologis atau sintesis yang menyatukan kedua perspektif, maka jawabannya hampir pasti tidak. Perbedaan yang ada terlalu mendasar untuk dijembatani tanpa menuntut salah satu pihak meninggalkan komitmen teologis intinya.
Namun, jika dialog yang bermakna dipahami sebagai upaya menuju pemahaman yang lebih mendalam atas perspektif pihak lain, apresiasi terhadap logika internal dan koherensi sistem teologis yang berbeda, keterbukaan untuk belajar dari kritik yang datang dari luar tradisi sendiri, serta kemampuan untuk hidup berdampingan secara hormat meskipun terdapat perbedaan yang tidak terelakkan, maka dialog semacam itu bukan hanya mungkin, melainkan juga sangat diperlukan.
Roma 3:1–20 beserta respons Islam terhadapnya menyediakan sebuah studi kasus yang sangat representatif bagi jenis dialog ini. Perikop tersebut memaksa pembaca untuk bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar dalam eksistensi manusia, yaitu siapakah Allah? Apakah kondisi manusia di hadapan-Nya? Di manakah letak masalah terdalam manusia? Bagaimana pemulihan itu dimungkinkan? Apakah fungsi hukum moral? Bagaimana relasi antara usaha manusia dan rahmat ilahi? Dan bagaimana manusia dapat hidup dalam damai dengan Allah?
Baik tradisi Kristen maupun Islam menawarkan jawaban yang komprehensif, koheren, dan reflektif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Meskipun jawaban-jawaban itu sangat berbeda, justru dalam perbedaan itulah dialog teologis menemukan maknanya; bukan sebagai sarana untuk meniadakan perbedaan, melainkan sebagai ruang untuk memahami, menguji, dan menghayati iman masing-masing dengan kedalaman dan kejujuran yang lebih besar.
Bagi umat Muslim yang bergumul dengan Roma 3:1–20, teks ini dapat menjadi kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam mengapa umat Kristen percaya seperti yang mereka yakini, menelusuri logika internal teologi rasul Paulus, serta mengapresiasi keseriusan pergumulan Kristen dengan persoalan dosa, keadilan, dan kasih karunia bahkan sambil tetap menolak jawaban teologis yang ditawarkan oleh rasul Paulus.
Sebaliknya, bagi umat Kristen yang mau mendengarkan kritik Islam, dialog ini membuka ruang untuk menyadari bahwa teologi yang bagi mereka tampak jelas dan koheren ternyata dapat dipandang sangat problematis dari perspektif lain. Kritik tersebut dapat berfungsi sebagai cermin teologis, yang menantang asumsi-asumsi yang kerap diterima begitu saja dan menajamkan pemahaman iman melalui perjumpaan dengan alternatif konseptual yang serius dan konsisten.
Lebih dari itu, dialog Kristen–Islam seputar Roma 3:1–20 mengingatkan kita bahwa perbedaan teologis yang mendalam tetap menjadi realitas dalam dunia kontemporer. Pertanyaan tentang kebenaran religius tidak dapat diselesaikan hanya dengan niat baik atau bentuk pluralisme yang naif. Baik Kristen maupun Muslim sama-sama mengklaim memiliki kebenaran yang final dan universal tentang Allah dan keselamatan. Klaim-klaim tersebut tidak mungkin semuanya benar secara bersamaan.
Namun demikian, kedua komunitas ini hidup di dunia yang sama dan menghadapi tantangan kemanusiaan yang sama. Karena itu, mereka dituntut untuk menemukan cara hidup berdampingan secara bermartabat: mengejar keadilan bersama, menghadapi krisis moral dan sosial bersama, serta memperlakukan satu sama lain dengan hormat yang layak bagi sesama manusia sebagai ciptaan Allah yang berharga.
Dialog mengenai Roma 3:1–20 dan respons Islam terhadapnya, apabila dijalankan dengan kejujuran intelektual, kerendahan hati, dan komitmen tulus untuk memahami, dapat memberikan kontribusi nyata bagi tujuan tersebut. Dialog semacam ini tidak akan menghapus perbedaan teologis yang mendasar, tetapi dapat membangun jembatan pemahaman manusiawi, menumbuhkan rasa hormat di tengah ketidaksetujuan, dan mengingatkan semua pihak bahwa misteri Allah yang tak terbatas melampaui kemampuan sistem teologis mana pun untuk sepenuhnya menangkap dan mengekspresikannya. Dalam kerendahan hati di hadapan misteri itu, terbuka ruang bagi dialog yang sungguh bermakna, bahkan di tengah perbedaan yang tidak dapat diperdamaikan.
Pertanyaan:
- Jika hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, mengapa hukum yang sama tidak mampu membenarkan manusia, dan bagaimana hal ini selaras dengan keadilan Allah?
- Jika tidak seorang pun benar dan tidak seorang pun mencari Allah, bagaimana manusia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi yang tidak ia pilih, dan atas dasar apa Allah memberi kasih karunia kepada sebagian orang saja?
- Apakah rasul Paulus menafsirkan Mazmur dan Yesaya secara setia terhadap konteks aslinya, ataukah ia menguniversalkan teks-teks kontekstual demi mendukung agenda teologisnya?
- Bagaimana pernyataan Yesus bahwa hukum Taurat tidak ditiadakan dapat direkonsiliasikan dengan ajaran rasul Paulus bahwa pembenaran terjadi terlepas dari hukum Taurat?
- Jika keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus, bagaimana keadilan Allah dipertahankan bagi mereka yang hidup sebelum Kristus atau tidak pernah mendengar Injil?
- Jika pembenaran tidak bergantung pada perbuatan, apa yang secara teologis mencegah kesimpulan bahwa perbuatan moral tidak relevan bagi status seseorang di hadapan Allah?
- Atas dasar otoritas apa teologi Paulus harus diterima sebagai normatif, mengingat ia tidak mengenal Yesus secara historis dan pengalamannya bersifat subjektif?
- Apakah antropologi rasul Paulus yang menekankan kerusakan total manusia tidak berisiko melahirkan keputusasaan moral dan menafikan kebajikan nyata pada manusia non-Kristen?
- Jika semua manusia sama-sama berdosa, mengapa keselamatan dibatasi pada satu jalur historis dan partikular, dan bagaimana hal ini mencerminkan kasih Allah yang universal?
- Secara rasional dan empiris, apakah konsep dosa asal atau fitrah manusia yang lebih koheren dalam menjaga keadilan Allah, tanggung jawab moral manusia, dan dasar etika?
Pdt. Em. Yohanes Bambang Mulyono
 Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi
Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi